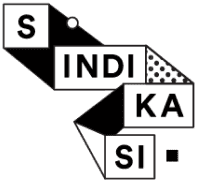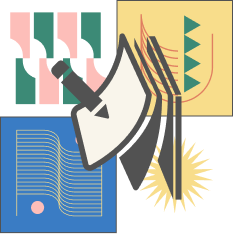Pandemi dan Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan

Jurnalis perempuan mendapat tekanan lebih besar saat menjalankan kerja jurnalistik selama pandemi Coronavirus Disease-19. Kebebasan pers berada di bawah ancaman yang lebih besar.
Tekanan terhadap jurnalis dan media lebih kompleks karena tidak hanya datang dari aktor negara, melainkan juga aktor non-negara. Medium dan cara pelaku kekerasan menyerang jurnalis berkembang, dari serangan langsung atau offline ke serangan online melalui media sosial.
Dua jurnalis perempuan di Yogyakarta, Dipna Videlia Putsanra dan Deatry Kharisma Karim mendapat pernah serangan saat meliput larangan pendirian kantor Gereja Klasis di Kabupaten Gunung Kidul pada 14 November 2020. Jurnalis perempuan lebih rentan saat meliput isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan karena dominasi kekuasaan dalam budaya patriarki.
Sekelompok orang dari organisasi masyarakat yang mengaku mewakili agama Islam, mayoritas laki-laki mengelilingi dua jurnalis saat mereka mewawancarai kepala dusun di Gunung Kidul. Kepala dusun tersebut punya pengaruh menyuburkan praktek intoleransi dan kelompok intoleran. Sekelompok orang itu melarang keduanya merekam. Mereka juga meminta kartu tanda penduduk, kartu pers, hasil rapid tes, memotret dan memvideokan liputan keduanya.
Dipna, jurnalis Tirto menulis tentang perjuangan kalangan minoritas berbasis agama melawan intoleransi. Sementara itu, Deatry, jurnalis pers kampus, Balairung Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menulis aktor yang menolak pendirian kantor Gereja Klasis.
Selain melarang merekam, kelompok intoleran itu juga menyerang identitas Dipna sebagai jurnalis yang beragama Katolik. Mereka menanyakan agama Dipna yang tidak relevan dengan kerja-kerja jurnalistik.
Setiap orang semestinya menghormati berbagai perbedaan atas dasar agama, keyakinan, dan identitas gender. Juga berpikir jernih tanpa prasangka dan kebencian.
Serangan terhadap dua jurnalis perempuan itu menggambarkan adanya pembatasan liputan yang mengganggu kebebasan pers di Indonesia. Pembatasan ini menunjukkan sebagian masyarakat belum memahami kerja jurnalis yang mendapat perlindungan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Menulis isu kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat penting untuk publik karena bersinggungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh konstitusi. Tapi, faktanya banyak terjadi pengabaian dan pelanggaran terhadap kelompok minoritas berbasis agama, keyakinan, dan identitas gender.
Di Yogya, selain larangan pendirian kantor GKJ Klasis, ada juga pencabutan izin mendirikan bangunan Gereja Sedayu dan saat ini pendeta Sitorus sedang pontang panting membangun gereja di tempat baru setelah IMB dicabut. Pada Oktober tahun lalu jmuncul surat berisi penolakan pemasangan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru di kampung Kauman Yogyakarta.
Gangguan terhadap kebebasan pers itu menjadi catatan buruk bagi Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta. Laporan atau catatan akhir tahun 2020 AJI Yogyakarta menempatkan peristiwa itu sebagai salah satu pengganggu kerja jurnalis.
Meliput kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan perkara mudah. Isu ini sangat kompleks karena menyangkut banyak lapis pelanggaran HAM. Aktornya bisa dari kalangan pemerintah dengan kebijakan yang tidak melindungi kelompok minoritas berbasis agama dan keyakinan. Pengganggu bisa juga dari kelompok-kelompok intoleran yang menebar teror, ancaman, dan kekerasan.
Potret kekerasan terhadap jurnalis perempuan juga terlihat dari hasil survei AJI Indonesia pada Agustus 2020. Mayoritas jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan seksual.
Sebanyak 25 jurnalis mengalami kekerasan seksual dari 34 responden jurnalis perempuan yang mengisi survei di sejumlah kota. Pelaku kekerasan mulai dari narasumber pejabat publik dan atasan di kantor tempat jurnalis itu bekerja.
Di tingkat global, jurnalis perempuan yang menulis isu-isu kritis menyangkut kepentingan publik menjadi target ancaman dan kekerasan. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO bersama International Center For Journalists menerbitkan laporan pada 10 Desember tentang kekerasan terhadap jurnalis.
Survei global itu menggambarkan sebanyak 73 persen jurnalis perempuan mengalami kekerasan online, 25 persen mendapatkan ancaman kekerasan fisik, 18 persen mengalami ancaman kekerasan seksual, dan 20 persen diserang secara offline setelah mereka mendapatkan kekerasan online. (https://en.unesco.org/news/unescos-global-survey-online-violence- against-women-journalists)
UN Women menyebutkan satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual, pelecehan verbal, dan serangan psikologis.
Data-data kekerasan terhadap jurnalis perempuan selama pandemi menunjukkan masalah serius yakni serangan terhadap kebebasan pers.
Jurnalis perempuan mengadapi hambatan berlapis untuk melaporkan liputan mereka secara aman.
Jurnalis perempuan perlu mengenali ancaman atau potensi kekerasan, mengantisipasinya, dan mengatasinya bila dia mendapatkan serangan. Redaksi di tempat mereka bekerja bertanggung jawab terhadap keselamatan setiap jurnalis.
Mereka perlu membekali jurnalis dengan membuat pedoman atau standar keselamatan diri saat melakukan liputan konflik. Organisasi profesi jurnalis perlu membuat banyak pelatihan tentang keselamatan jurnalis dan melakukan advokasi lebih serius karena serangan semakin berkembang.
Saya berharap tidak terjadi lagi upaya pembatasan liputan karena membuat publik tidak mendapatkan informasi yang utuh. Semua kalangan perlu bekerja keras memutus mata rantai kekerasan terhadap jurnalis perempuan untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik. Tidak ada berita seharga nyawa karena keselamatan lebih utama.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta dan bekerja sebagai Koresponden Tempo