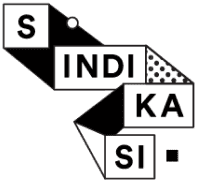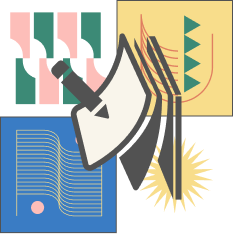Kesetaraan dalam Pekerjaan bagi Perempuan dan Kelompok Minoritas

Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain norma gender dan label terhadap perempuan, situasi kompleks pun ikut meningkatkan kerentanan perempuan terkait eskalasi krisis multi-dimensi seperti konflik, bencana, pencemaran lingkungan, pengkambinghitaman minoritas gender dan seksual, dan lain-lain. Komnas Perempuan (2021) mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang 2020 mencapai 299.911 kasus. Data pengaduan ke lembaga tersebut meningkat sekitar 60 persen dari 1.413 kasus (2019) menjadi 2.389 kasus (2020). Dari total kasus, terdapat 2.134 kasus kekerasan berbasis gender. Selain tingginya kasus di ranah personal, kasus di ranah publik mempunyai angka yang mencengangkan. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi di ranah publik.
Pada akhir 2020, Konde.co melakukan riset terhadap isu kekerasan seksual di tiga media online terbesar di Indonesia. Hasilnya menunjukkan media tidak konsisten memberitakan isu kekerasan seksual yang berperspektif keadilan bagi korban. Media kerap melakukan sensasionalisme kekerasan seksual tanpa memikirkan kepentingan atau kondisi psikologis korban serta mengabaikan perspektif perempuan.
Sementara itu, menurut survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta awal 2021 terhadap kekerasan seksual di kalangan jurnalis (34 orang jurnalis dengan 31 di antaranya perempuan), sebanyak 25 orang pernah mengalami kekerasan seksual. Namun, sebagian besar korban mengaku tidak pernah melaporkan kasusnya dengan alasan lingkungan yang tidak mendukung hingga kondisi psikologis korban.
Untuk mengenal lebih lanjut tentang situasi tersebut, dua sosok perempuan dengan identitas dan latar belakang yang berbeda, bersedia angkat suara dan berbagi kisah.
Kisah Putri, Jurnalis Televisi
“Di industri (media), kami (pekerja perempuan) minoritas. Kameramen, penata lampu, editor, dan lain-lain itu rata-rata cowok,” ungkap Putri, seorang jurnalis perempuan yang bekerja di sebuah stasiun televisi di Jakarta.
Di tengah lingkungan kerja yang laki-laki, pelecehan seksual sering dialami Putri, mulai dari colekan, senggolan pada tangan atau paha, rangkulan atas dalih keakraban, godaan verbal, sampai stiker bernuansa seks yang dikirimi melalui gawai pintar, baik itu oleh rekan sesama jurnalis maupun narasumber yang laki-laki. Ia pun menggambarkan situasi tempat kerjanya yang ia ibaratkan selayaknya boys-club – suatu ruang yang didominasi oleh pria.
“Setiap liputan ke luar kota, sepanjang perjalanan itu yang dibahas cewek seksi,” ungkapnya. Dalam melaksanakan tugas, Putri biasanya menjadi satu-satunya perempuan di dalam tim. “Reporter cewek dilecehkan secara fisik habis-habisan. Standar kecantikan juga parah. Enggak boleh gendut di depan kamera.”
Ia pernah menyampaikan keluhan pada bagian sumber daya manusia atau HRD (human resource department) di kantornya tentang hal tersebut. Tapi, bukannya mendapat tanggapan yang positif, pelecehan seksual yang dilakukan sesama pekerja laki-laki terhadap perempuan dianggap normal.
“Namanya juga cowok. ‘Kan normal ngomong begitu,” kata Putri meniru omongan staf HRD-nya ketika ia mengadukan rekan kerjanya yang kerap melakukan pelecehan secara lisan. Ia malah dianggap bermental lemah dan kurang mampu beradaptasi karena mengeluhkan perkara pelecehan seksual.
Kisah Zara, Penyiar Radio & Pekerja Kreatif
Zara adalah seorang transpuan yang sempat kuliah di jurusan penyiaran dan kini tinggal di Bekasi.
Zara mengawali kisahnya saat ia bekerja sebagai penyiar sekitar tahun 2016 lalu. Ketika melamar pekerjaan tersebut, ia sudah melakukan transisi dengan identitas dan ekspresi gender perempuan. “Aku melamar pakai identitas KTP dan ijazah dengan nama lahir dan jenis kelamin lelaki,” ungkapnya bercerita tentang proses rekrutmen. “Waktu aku datang, yang punya radio awalnya enggak ngeh (menyadari) aku transpuan. Tapi, begitu melihat data aku, ia melihat aku dari atas sampai ke bawah dengan sinis. Jadi aku pasrah saja kalau enggak diterima. Dia bilang, ‘Kamu bisa kerja kayak begini (sebagai penyiar)?’ Saya bilang bisa dan saya kuliah jurusan broadcasting.”
Zara diterima bekerja. Ia diizinkan untuk memakai identitas perempuan dan menggunakan nama yang tidak sesuai KTP. Beberapa bulan bekerja, semua berjalan lancar hingga rekan-rekan kerjanya di kantor mulai membicarakannya sebagai waria. Tatapan melecehkan juga kerap ia terima ketika solat dengan mukena.
“Kalau lagi ngobrol aku sering ditanya soal pacar. Aku gerah karena ditanya kalau pacaran kayak bagaimana,” ungkap Zara. Saat itu, ia menyadari dirinya tengah dijadikan bahan lelucon dan tak lama setelah itu, ia memutuskan berhenti.
Tapi, itu bukan pengalaman terakhirnya. Zara sempat lanjut bekerja di sebuah perusahaan air mineral kemasan. Dan pelecehan seksual yang ia dapatkan, datang dari atasannya sendiri yang kerap menunjukkan padanya video porno dan melontarkan kata maupun godaan seksual. Zara pun pernah menangis ketika atasannya menampar dan meremas bokongnya secara tiba-tiba ketika tengah berpapasan di kantor.
“Aku jadi trauma cari pekerjaan di sektor formal. Ketika aku memiliki skill, terhambat dengan identitas gender aku,” ungkap Zara yang pernah bekerja sebagai pekerja seks dengan situasi yang tak selalu lebih baik tanpa adanya pengakuan maupun jaminan perlindungan.
Fenomena kekerasan dan pelecehan seksual memang bukan hal baru. Meski begitu, tak banyak kasus yang didokumentasikan. Banyak korban memilih diam karena seringkali berada di situasi yang tidak berpihak pada mereka. Kekerasan dan pelecehan seksual pun dianggap seolah wajar. Apalagi, banyak pihak perusahaan tidak memiliki mekanisme pengaduan dan tidak menjadikan kekerasan dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran yang harus ditindak.
Dari pengalaman Putri maupun Zara, kita lihat perempuan dan kelompok minoritas tidak selalu memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan. Di media televisi, jurnalis atau reporter perempuan dilekatkan dengan standar kecantikan tertentu, termasuk berat badan. Sementara itu, kemampuan seorang transpuan diragukan hanya karena identitas dan ekspresi gendernya. Mereka juga harus berhadapan dengan berbagai tindak kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja yang dilakukan atasan maupun rekan kerjanya.
Panduan EEO dan Dorongan Kesetaraan dalam Pekerjaan
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa setiap orang, baik lelaki maupun perempuan, berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (Pasal 28D ayat (2)) Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang Sama untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Penegasan lain disebutkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang menyebutkan bahwa setiap pekerja (buruh) berhak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan serta perlakuan yang sama dari pengusaha tanpa diskriminasi. (Pasal 5 dan Pasal 6) Bahkan, pada Oktober 2005, Indonesia mengeluarkan “Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang sama dalam Pekerjaan di Indonesia” (biasa disebut dengan Panduan EEO) untuk lebih memantapkan aspek kesetaraan gender dalam pekerjaan.
Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan atau disebut Equal Employment Opportunity (EEO), mencakup segala kebijakan termasuk pelaksanaannya yang bertujuan untuk penghapusan diskriminasi di dunia kerja, baik itu yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung karena karakteristik gender atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. EEO adalah prinsip kesetaraan dan diperkenalkan oleh International Labour Organization (ILO) untuk pula mempromosikan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan (penghapusan diskriminasi) dalam ketenagakerjaan.
Dalam Panduan EEO yang diterbitkan Gugus Tugas EEO, dirinci bagaimana penerapan EEO sesungguhnya mampu memberikan manfaat dan keberhasilan bagi perusahaan. Panduan tersebut pun menguraikan perihal EEO dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja serta hal-hal terkait dengan hubungan kerja.
Pada pengantarnya, Gugus Tugas EEO mengatakan panduan yang telah disepakati oleh serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu ditujukan untuk memberikan arahan bagi perusahaan dalam melaksanakan dan mendukung upaya kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan di Indonesia, khususnya penghapusan diskriminasi dalam hal jenis kelamin.
Namun, meski telah berumur lebih dari 15 tahun, panduan tersebut tampaknya belum banyak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penghapusan kekerasan seksual di tempat kerja.
Saat ini, ILO bersama konstituen tripartitnya pun tengah berproses melakukan pembaharuan terhadap Panduan EEO untuk bisa disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja, terutama terkait adopsi Konvensi Kekerasan dan Pelecehan Seksual No. 190 Tahun 2019 (Konvensi ILO No. 190) dan Rekomendasi No. 206. Perubahan terhadap Panduan EEO pun diharapkan dapat pula menegaskan inklusi sosial atau kelompok minoritas lain, termasuk penyandang disabilitas, orang dengan HIV (ODHIV), Masyarakat Adat, LGBTIQ+, dan lainnya.
Tentu saja, tanpa terlepas dari itu, perjuangan terhadap pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan ratifikasi Konvensi ILO No. 190, menjadi pula bagian penting dalam mendukung kesetaraan bagi semua, terutama pekerja perempuan dan minoritas.
***
Unduh Panduan EEO pada tautan berikut ini: https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_122029/lang–en/index.htm
Peneliti dan penulis lintas isu. Ia baru saja mengeluarkan buku berjudul Rumah di Tanah Rempah (Gramedia, 2020). Kini, menjabat sebagai Koordinator Divisi Gender SINDIKASI. Twitter: @nurdiyansah