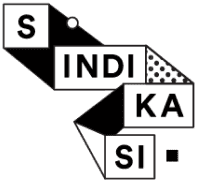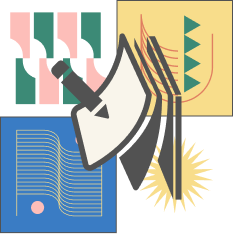Upah Murah Perempuan

Oleh Nurjanti
Kesenjangan upah antar gender masih menjadi masalah di seluruh dunia. Organisasi perempuan PBB, UN Women, mencatat secara global kesenjangan upah antar gender mencapai 16 persen pada 2020. Di Indonesia, seperti dirilis UN Women dan organisasi buruh internasional, ILO, perempuan memiliki pendapatan 23 persen lebih rendah dari lelaki. Berarti, bila pekerja lelaki mendapat 100 persen, perempuan hanya mendapat 77 persen upah dengan beban kerja yang sama.
Kondisi ini diperparah oleh krisis selama pandemi Covid-19. Diperkirakan, krisis ekonomi akibat pandemi dapat mendorong 96 juta orang ke dalam garis kemiskinan. Bila prediksi tersebut terjadi, jumlah wanita dan anak perempuan yang hidup dengan USD 1,90 per hari akan bertambah menjadi 435 juta jiwa pada 2021.
Perempuan juga bekerja tiga kali lebih banyak dari lelaki. Selain pekerjaan yang menghasilkan upah, perempuan juga harus melakukan kerja-kerja reproduksi sosial, seperti memasak, merawat anak, membersihkan rumah, dan pekerjaan lainnya yang meskipun punya peran penting dalam menjalankan fungsi keluarga dan keberlangsungan ekonomi, namun tidak dianggap. Pada ibu akhirnya mendapat upah lebih sedikit karena waktu kerjanya produktifnya dianggap lebih sedikit dan pekerjaannya hanya dianggap sebagai pemasukan tambahan.
Kesenjangan upah tak banyak berubah sejak jalan menciptakan pengupahan yang adil bagi pekerja lelaki maupun perempuan di mulai pada 1950-an. Dalam sidang konferensi ILO ke-34 di Jenewa salah satu usulan yang dibahas ialah prinsip pengupahan yang setara. Sidang ini kemudian menghasilkan Konvensi Internasional C100 tentang kesetaraan upah yang ditetapkan pada 29 Juni tahun 1951.
Enam tahun kemudian setelah desakan dari para buruh, Indonesia mengeluarkan UU No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya. UU ini ditandatangani pada pada 31 Desember 1957.
Sebelum pemerintah meratifikasi konvensi ILO, UUDS 1950 pasal 28 ayat 3 sudah menjamin bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama berhak atas pengupahan yang sama. Perhatian tentang kesenjangan upah antar gender juga sudah disuarakan sejak paruh pertama dekade 1950-an. Jafar Suryomenggolo dalam bukunya Politik Perburuhan Era Demokrasi Liberal 1950an menyebut persoalan kesenjangan upah menjadi perhatian utama bila membahas persoalan ketidakadilan di tempat kerja pada dekade 1950-an.
Pada akhir 1952 tercatat persoalan kesenjangan upah diajukan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) oleh serikat buruh industri tekstil yang didominasi oleh perempuan. Dalam perselisihan antara Serikat Buruh Tekstil yang berdomisili di Bandung dan NV (sejenis PT) Waverij Yoeng Ngi di Jakarta masalah kesenjangan upah menjadi salah satu tuntutan di samping kenaikan upah dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Sebelumnya, pada Maret 1951, para buruh memiliki perjanjian dengan perusahaan bahwa perusahaan tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif. Sehingga kesenjangan upah merupakan pelanggaran pada perjanjian karena perusahaan tidak boleh memberikan “perbedaan penghargaan”.
Perjanjian tersebut seperti dikutip Suryomenggolo berbunyi, “Pihak pengusaha tidak mengadakan perbedaan bangsa dan penghargaan, bilamana terdapat tindakan dan aturan yang dianggap oleh pihak buruh ada perbedaan, pihak buruh diberi kesempatan untuk memberitahu kepada pengusaha”.
Ketika dibawa ke tingkat daerah, P4 Daerah menerima alasan perusahaan bahwa tidak ada pembedaan penghargaan meskipun faktanya perusahaan mengupah buruh lelaki sebanyak empat rupiah per hari sementara buruh perempuan hanya menerima 3,5 rupiah. Karena keputusannya dirasa janggal, para buruh kemudian mengajukan banding ke P4 Pusat. Hasilnya, perusahaan diwajibkan untuk menetapkan upah terendah empat rupiah per hari dan melarang perusahaan untuk memberikan perbedaan penghargaan antara buruh lelaki maupun perempuan untuk pekerjaan yang sifatnya sama.
Sementara di Amerika Serikat, UU yang mengatur kesetaraan upah keluar pada 1963 setelah mendapat pertentangan dari kalangan pengusaha. Kamar Dagang dan Asosiasi Pedagang Ritel menolak keras UU tentang kesetaraan upah ini. Sementara Esther Peterson, kepala Biro Wanita di Departemen Tenaga Kerja, dan mantan Ibu Negara Eleanor Roosevelt, amat mendukung UU ini.
Pada 1963 kongres akhirnya mengesahkan Undang-Undang Kesetaraan Upah yang melarang diskriminasi pengupahan berdasar jenis kelamin pada buruh yang terlibat dalam produksi barang untuk perdagangan. Selain itu, pada 1964 terbit pula Undang-Undang Hak Sipil, yang melarang pemberi kerja melakukan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal negara.
Dalam Equal Pay: A Thirty-Five Year Perspective mencatat aturan tentang kesetaraan upah kemudian meluas ke pekerja administrasi, eksekutif, dan profesional lewat Amandemen UU Pendidikan 1972. Dua tahun setelahnya aturan kesetaraan upah makin meluas, menyasar pekerja sektor publik.
Di Inggris, isu kesetaraan upah sudah disuarakan sejak 1903 namun aturan terkait baru keluar pada 1970. Pay Justice, lembaga yang mengadvokasi kesenjangan upah berbasis gender menyebut, pemogokan buruh perempuan di pabrik Ford Degenham memicu disahkannya UU kesetaraan upah.
Protes buruh perempuan bermula ketika Ford Dagenham mengenalkan struktur pengupahan baru. Pekerjaan buruh perempuan yang memproduksi sarung jok mobil dikategorikan sebagai pekerjaan produksi kurang terampil (Kategori B) bukan kategori pekerjaan produksi lebih terampil (Kategori C). Selain itu mereka dibayar 15% lebih rendah dari rekan lelaki mereka dengan pekerjaan serupa.
Buruh-buruh perempuan kemudian mengadakan protes di London yang kemudian diikuti oleh para buruh lain. Pemogokan mereka mengakibatkan stok sarung jok mobil dan semua produksi mobil dihentikan. Protes para buruh mendapat perhatian secara nasional dan berakhir setelah tiga minggu. Hasilnya upah para perempuan dinaikkan meskipun belum setara dengan rekan lelaki mereka, menjadi 92 persen dari upah lelaki. Pemerintah juga menaruh perhatian hingga keluar UU Kesetaraan Upah pada 1970.
Sejarawan University of East Anglia Emma Griffins dalam opininya “What’s to blame for the gender pay gap? The housework myth” di The Guardian menyebut sejak berabad lalu kerja perempuan dinilai lebih rendah dari lelaki. Pembedaan upah berbasis gender kemudian menjadi jalan untuk mempertahankan status quo dengan memastikan bahwa di tiap rumah tangga terdapat tanaga perempuan yang akan memasak, mengasuh anak, dan membersihkan rumah. Terlepas dari tingkat pendidikan perempuan yang semakin tinggi dan angka partisipasi kerja yang meningkat, masalah ketidakadilan di tempat kerja akan terus berlanjut ketika upah setara belum dicapai.
Di tengah krisis pandemi, semakin banyak perempuan yang menghadapi kesulitan ekonomi. Perjuangan untuk mendapatkan upah yang adil menjadi makin mendesak karena mereka yang berpenghasilan paling rendah menjadi kelompok yang paling terdampak.