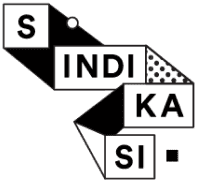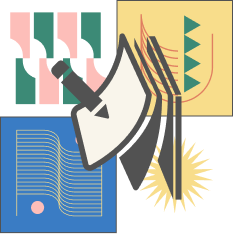Stereotip Perempuan dalam Media

Kapan perempuan pertama kali mendapatkan stereotipe sebagai orang yang mudah menangis, tidak mandiri, meledak-ledak emosinya, dan pemarah? Sejak ia lahir dan mengenal lingkungannya, atau sejak lingkungan membentuknya pada konstruksi hierarki gender yang melekat?
Stereotipe ini memproyeksikan pola pikir masyarakat pada tubuh perempuan. Pada rambut yang harus lurus dan panjang, pada mata yang harus lentik, pada bibir yang harus memerah ranum dan pada tubuh yang harus tinggi dan langsing. Kalangan feminis pasca-modern meyakini bahwa stereotipe terhadap perempuan tersebut kemudian dibesarkan oleh industri media.
Pendekatan feminis-strukturalis Simone de Beauvoir telah mengilhami Ortner (1974) dalam menilai bahwa subordinasi perempuan secara universal adalah dampak dan fungsi khas mereka dalam tradisi dan budaya yang melekat di masyarakat. Perempuan dianggap sebagai pengasuh dan orang yang membesarkan anak. Perempuan juga selalu diidentifikasi pada ranah rumah tangga.
Pada posisi yang berbeda, hieraki gender menempatkan laki-laki sebagai gender yang perkasa, selalu menang, tak pernah menangis, dan hanya bertanggungjawab secara publik—bukan secara domestik. Hal inilah yang membuat orang-orang di luar hierarki menjadi kesulitan untuk diterima dalam nilai-nilai tersebut. Padahal, di luar dua kelompok gender tersebut ada juga kelompok lesbian, gay, biseksual, transeksual (LGBT), yang keberadaannya dipinggirkan.
Konstruksi gender dalam konteks patriarki membuat perempuan sulit untuk mengubah“takdirnya”. Bukan hanya perempuan, orang-orang yang hidup di luar hierarki gender pun terpinggirkan; kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), misalnya, menjadi sulit diterima dan sulit dibahasakan di kalangan masyarakat.
Di Barat, hierarki gender terjadi sejak manusia mengkonstruksikannya. Walau pun konstruksi ini terus berubah, namun sepanjang sejarah—sejak masa pemerintahan demokrasi modern Pericles di Yunani, masa Revolusi Industri di Eropa di abad 16, hingga sekarang—perempuan tak pernah lepas dari penilaian, dari konstruksi. Konstruksi ini pun merasuk dalam seni dan kebudayaan sehari-hari. Pada masa Revolusi Industri, konstruksi ini mengemuka dalam Monalisa karya Leonardo da Vinci. Hari ini, mengejawantah dalam boneka Barbie.
Stereotipe yang melekat pada perempuan dan hierarki gender yang baru ini kemudian menimbulkan sejumlah persoalan baru yang terjadi di masyarakat. Misalnya, perempuan mengalami berbagai hambatan karena nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat membatasi akses dan kesempatannya. Stereotipe inilah melestarikan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan industri media kita merupakan propagandis terdepan dalam mengkampanyekan stereotipe tersebut.
Peran Media
Dalam media di Indonesia stereotipe ini melekat dalam berbagai tayangan; dari sinetron, infotainment, telewicara, hingga berita. Gambaran tentang perempuan pemarah, pencemburu, pendendam ada dalam tayangan sinetron. Tayangan infotainment memprogandakan pasangan sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan perempuan. Jika seorang artis perempuan tidak berpasangan, maka ia akan terus dikejar-kejar pertanyaan pekerja infotainment. Status lajang menjadi status buruk bagi perempuan yang dilekatkan oleh infotainment di televisi kita.
Hal lainnya adalah status cantik yang melekat dalam industri media televisi. Siapa saja yang tampil menjadi selebritas di televisi harus selalu cantik. Jika tak cantik, maka seorang perempuan akan mendapatkan ejekan: tak seksi, kurang putih, mukanya kurang menjual, kalah pamor dari perempuan cantik lainnya.
Stereotipe cantik ini tidak hanya terjadi dalam industri periklanan, namun telah menjalar di ruang-ruang redaksi di pemberitaan televisi—stereotipe yang sangat jarang terjadi di ruang redaksi di media cetak maupun radio.
Stereotipe yang berkisar dalam hal kecantikan inilah yang akhirnya membuat perempuan membenci tubuhnya. Para perempuan membenci wajahnya yang kurang cantik, kakinya yang kurang panjang dan tubuhnya yang terlalu gemuk. Akibatnya, perempuan menjadi pemimpi—ingin berubah wujud menjadi tubuh yang diinginkan industri. Karena prasyarat cantik inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan identitas seseorang, yaitu dengan simbol-simbol, signifikasi, representasi dan semua bentuk citra. Kriteria inilah yang sering dilabelkan bagi pada seseorang atau kelompok tertentu.
Tak hanya itu, industri media kemudian memecah-belah perempuan. Ada pengkotak-kotakkan: perempuan berwajah cantik vs perempuan berwajah pas-pasan, perempuan putih vs perempuan berkulit hitam. Dan ini kemudian dibesarkan oleh mode, fashion dan juara ratu-ratuan sejagat. Media televisi, dalam kultur indutri di Indonesia turut membesarkannya.
Hal ini bisa kita lihat dari periodisasi pers di Indonesia. Dari perspektif perempuan, pers di Indonesia memang telah mengalami dua periode yang memprihatinkan.
Pada era Orde Baru, media berada dalam kekangan pemerintah. Pers dilarang untuk kritis, tidak ada kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat. Kondisi ini juga membuat minimnya penguatan perempuan di media. Isu perempuan dikonstruksikan sesuai selera pasar. Banyak media massa yang muncul hanya menawarkan konsumerisme dan justru mengkonstruksikan kembali perempuan sebagai orang mengurus domestik. Selain itu lebih banyak media di jaman Orde Baru menuliskan perempuan sebagai bagian dari gaya hidup modern. Ini adalah periode terburuk dalam kehidupan pers berperspektif perempuan di Indonesia.
Sejak peristiwa reformasi 1998 hingga saat ini, katup kebebasan yang dulu tertutup dibuka lebar untuk pers. Namun saat ini pers di Indonesia tumbuh secara liberal. Pada masa ini, seharusnya suara publik/masyarakat banyak didengar, namun justru yang terjadi sebaliknya: media hanya melayani informasi terkait kehidupan elit, merendahkan perempuan melalui tayangan sinetron, berita dan iklan yang bias gender. Perempuan masih dikonstruksikan di dalam sinetron, iklan dan berita secara sretereotip sebagai orang yang emosional, cerewet, sangat senang mengurusi persoalan personal orang lain, cengeng.
Dalam dua periode tersebut, siaran informasi dan komunikasi yang sehat bagi publik perempuan yang seharusnya diproduksi sebagai wujud demokratisasi media, sangat jarang kita lihat. Yang terjadi, perempuan dilihat hanya sebagai konsumen. Dalam media online, perempuan banyak mendapatkan kekerasan dan stereotiping.
Jaminan Negara
Media merupakan salah satu klausul dalam pembahasan 12 isi deklarasi Beijing Platform for Action, sebuah deklarasi internasional yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menumbuhkan kesetaraan, pembangunan, serta perdamaian dunia. Dalam konferensi regional perempuan Beijing+20 di Bangkok tahun 2014, serta konferensi yang sama di tingkat internasional di New York tahun 2015, stereotipe perempuan di media merupakan salah satu pembahasan utama. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara peserta dalam konferensi yang diadakan PBB ini.
Dalam putusannya, konferensi di tingkat regional Asia Pasifik kemudian mengeluarkan putusan untuk klausul perempuan dan media. Putusan tersebut berbunyi: “Pemerintah akan menjamin tidak adanya stereotipe di media yang mengakibatkan pada diskriminasi terhadap perempuan di media, dan Pemerintah akan membuka partisipasi terhadap perempuan di media dan dalam menggunakan teknologi. Pemerintah juga memastikan tidak terjadi kesenjangan dalam penggunaan teknologi dan adanya kebebasan berekspresi.”
Jika kita runut tentang persoalan yang terjadi di media di Indonesia serta komitmen pemerintah tentang ini, ada 3 persoalan yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki nasib perempuan melalui media.
Pertama, pemerintah harus menjamin adanya partisipasi yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam media. Kedua, Pemerintah harus menjamin adanya perbaikan pada nasib buruh perempuan media. Ketiga, Pemerintah harus menjamin bahwa media tidak digunakan untuk kepentingan ekonomi-politik pemilik media semata. Mengapa pemerintah harus menjamin soal ini?
Dalam era konglomerasi hari ini, media yang digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi para pemiliknya sangat berorientasi pada pasar, karena ritme politik pemilik media selalu didukung oleh ritme ekonomi.
Logika ini kemudian juga melihat bahwa berita yang “besar” adalah berita yang mendatangkan banyak keuntungan, dan berita yang “kecil” adalah berita yang tidak mendatangkan rating/share, klik, dan oplah yang besar. Orientasi inilah yang terjadi hingga sekarang.
Dalam skala 15 tahun sesudah reformasi, orientasi industri tampak di sejumlah media di Indonesia. Media online yang tumbuh dengan menyajikan berita yang menjual sensasi dan menjadikan perempuan sebagai objek berita. TV meraup untung dengan menayangkan sinetron dan infotainment yang mengubek-ubek kehidupan pribadi. Di luar orientasi pasar yang sering didaku sebagai penyebab tayangan diskriminatif ini, media—pertelevisian kita, terutama—disetir pula oleh orientasi politik pemiliknya. Televisi telah menjadi panggung politik bagi para pemilik medianya. Maka tak heran jika ada pemilik media yang kemudian berseliweran berpidato atas nama partainya atau hotel dan resto yang dibangunnya.
Sistem pers demokratis merupakan cita-cita bersama. Secara umum, pers demokratis tidak menyerahkan mekanisme pers pada pasar, dan tidak menyerahkan keperuntungannya pada pemilik media yang hanya mencari keuntungan ekonomi dan pemilik media yang berpolitik.
Negara seharusnya menjadi fasilitator keterbukaan masyarakat dan memfasilitasi berbagai regulasi serta penguatan regulator dalam konteks partisipasi masyarakat berperspektif gender dan menjamin independensi. Dengan demikian, berbagai persoalan masyarakat marjinal seperti perempuan, anak, korban HAM, buruh, nelayan, miskin kota, petani, difabel, dan LGBT, bisa masuk menjadi isu penting di media.
Tulisan ini pertama kali dimuat di Remotivi
Pemimpin Redaksi Konde.co dan Anggota Serikat SINDIKASI