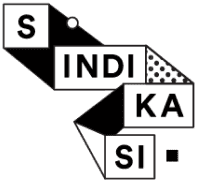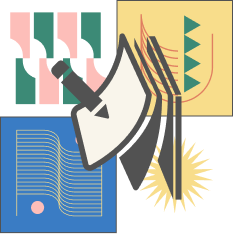Sri Wiyanti Eddyono: Kita Butuh Hukum yang Mengatur Penghapusan Kekerasan Seksual

Kamis (16/7), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) resmi dicabut dari Program Legislasi Nasional 2020. Banyak pihak menyampaikan kekecewaan dan kemarahannya atas sikap Komisi VIII yang menilai pembahasan RUU PKS sulit. Di media sosial, banyak perempuan yang angkat bicara soal pengalaman pelecehan dan kekerasan seksual yang mereka alami demi menunjukkan urgensi kehadiran undang-undang ini. RUU PKS ini padahal juga sangat penting mengingat perlindungan hukum mengenai korban kekerasan seksual belum diatur secara tegas dan berspektif korban.
Untuk mendapatkan perspektif lebih jauh mengenai RUU PKS, Citra Maudy dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) pada Selasa (14/7) berbincang dengan Sri Wiyanti Eddyono, dosen Fakultas Hukum UGM yang terlibat dalam perumusan naskah akademik RUU PKS. Perempuan yang akrab disapa Iyik ini pernah aktif cukup lama sebagai pengacara di LBH APIK dan punya banyak pengalaman mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual. Ia mengajak publik untuk terus memperjuangkan RUU PKS hingga disahkan.
Sejak kapan dimulainya usaha penghapusan kekerasan seksual? Apakah ini merupakan peraturan di tingkat negara yang pertama kali diajukan?
Setelah adanya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa di Jakarta tahun 1998, muncul inisiasi perlindungan hukum yang lebih memadai untuk perlindungan perempuan korban kekerasan seksual. Akan tetapi, saat itu belum dalam bentuk wacana undang-undang, masih dalam bentuk lembaga yaitu pembentukan Komnas Perempuan.
Kemudian kita mulai mengenakan isu kekerasan seksual, meskipun masih di ranah rumah tangga, yakni UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Itu tahun 2004. Tahun 2005, ada inisiatif lagi dari teman-teman Jaker-PKTP, khususnya LBH Apik, tentang RUU Perkosaan. Akan tetapi inisiatif itu tidak berlanjut karena tidak mendapatkan gerakan yang kuat.
Pada tahun 2007-2009, angka kekerasan seksual ini semakin tinggi. Akhirnya, Komnas Perempuan mulai melakukan pemetaan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tahun 2009. Hasilnya, tahun 2011, menunjukkan data tentang adanya 15 bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia. Tahun 2012, laporan terhadap 15 bentuk kekerasan seksual itu diluncurkan. Dari situlah muncul ide akan urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ada draft awal di tahun 2012 yang sudah sampai ke DPR tetapi belum menjadi pembahasan.
Tahun 2015, saya termasuk yang diminta oleh Komnas Perempuan untuk menyelesaikan naskah akademis dan membantu menyelesaikan draft RUU. Saat itu yang terlibat dalam pembuatan draftnya adalah Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, dan DPD. Draft itu selesai pada September 2016, lalu oleh Baleg diserahkan kepada DPR sebagai inisiatif DPR. Tahun 2017, RUU itu masuk ke Prolegnas. Semenjak titik ini, pembahasan yang dilakukan pemerintah mulai mengecewakan dan sayangnya mengalami kebuntuan.
Baru bulan Maret 2019, pemerintah di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan melakukan sedikit langkah maju. Itupun karena dorongan teman-teman, mengingat bulan Oktober masa kerja DPR sudah mau selesai. Bulan Maret-September mereka mulai menyusun draft. Akan tetapi, itu sudah terlalu terlambat karena Komisi VIII DPR sudah tidak mau membahasnya lagi karena kepelikan yang terjadi di internal. Nasib RUU PKS ini akhirnya dikeluarkan dari Prolegnas 2019 dan diusulkan menjadi Prolegnas 2020 tanpa carry over.
Ketika tahun 2020 baru dimulai, pembahasan ini stuck karena lagi-lagi dirasa tidak ada kesepahaman substansi antara pemerintah dan DPR perkara judul. Jadi, sebetulnya sejak Februari 2020 itu sudah mulai buntu. Bahkan, Maret sudah ada surat dari Komisi VIII yang berisi permintaan dikeluarkannya draft dalam Prolegnas. Tetapi, semakin mengerucut akhir-akhir ini. Pemerintah pun sifatnya menunggu. Itu juga yang saya sayangkan.
Mengapa negara perlu mengatur kekerasan seksual?
Harus, karena tindakan itu bentuknya kekerasan, jadi ada serangan. Kalau yang bentuknya tidak ada serangan, tidak apa-apa tidak diatur dalam kerangka pidana. Pelaku melakukan kriminalisasi melalui beberapa tindakan yang dianggap dapat menimbulkan harm (kerugian; penderitaan) kepada orang lain. Hal ini disebut sebagai bentuk kejahatan. Itukan ada 15 bentuk kekerasan seksual, tetapi yang diatur akhirnya hanya 9. Kesembilan jenis kejahatan ini melingkupi wilayah manapun termasuk tempat kerja. Misalnya, seperti siulan kepada perempuan. Itu kan sebetulnya juga kejahatan, tetapi dianggap tidak perlu diatur dan dibiarkan menjadi wilayah para tokoh agama dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Tetapi, kalau sudah sampai pada kejahatan harus diproses.
Banyak yang mengatakan kita tidak usah berharap pada pemerintah dan fokus saja pada penguatan dan kesadaran di komunitas, bagaimana pendapat Anda?
Jelas kita harus berdaya, memperkuat komunitas, dan melakukan kampanye. Sebagai perempuan kita perlu melakukannya. Tetapi itu tidak cukup. Kita tetap harus mendesak negara karena ini tanggung jawabnya. Kita perlu membangun sistem yang kuat dan adil agar ketika komunitas atau masyarakat tidak sanggup, masalah ini mendapat perlindungan dari negara.
Di dalam komunitas sendiri juga ada banyak kepentingan. Salah satu akibatnya adalah banyak kasus yang ditutup-tutupi demi rasa malu atau nama baik. Korban justru mendapat represi. Oleh karena itu, kita harus punya perlindungan di tingkat negara termasuk ketika ada desakan dari komunitas untuk menutupi kasus karena disebut aib, itu harus dilindungi. Padahal, harusnya yang aib kan pelaku, bukan korban.
Apakah hukum bisa mempengaruhi dan turut melanggengkan penindasan terhadap perempuan?
Bisa, hukum bisa bermata dua. Pada satu sisi, hukum bisa memberikan perlindungan, kalau hukumnya baik dan masyarakat hukumnya sadar. Itu terjadi bila budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum memang sudah baik. Akan tetapi, hukum juga bisa menciptakan situasi yang tidak ideal atau bahkan berkontribusi kepada disempowerment (pelemahan terhadap perempuan) ketika hukumnya jelek. Seperti sekarang inilah, jelek, banyak bolongnya, dan tidak sensitif terhadap perempuan. Begitupun dengan penegak hukumnya, masih bias gender atau blaming the victim (menyalahkan korban). Tidak hanya itu, bila undang-undangnya bagus, penegak hukumnya bagus, tetapi budaya hukum atau masyarakatnya belum baik seperti menghalang-halangi korban untuk melapor, bahkan menyalahkan korban, sistem hukumnya jadi tidak bekerja. Di situlah terjadi pelemahan terhadap perempuan.
Berarti, kesadaran komunitas maupun peraturan yang ada di atasnya itu penting untuk jalan bersamaan?
Harus. Semua pihak memang disarankan untuk membangun zero tolerance policy. Pencegahannya harus kuat, karena kalau tidak itu bisa menimbulkan terjadinya kasus. Bila sudah terjadi kasus, maka relatif costly, baik bagi korban, pendamping, lingkungan, bahkan secara psikologis juga bisa terganggu, hitung-hitungan ekonomisnya sudah berbeda. Oleh sebab itu pencegahan harus diutamakan. Tidak ada yang mau juga mengalami pelecehan dan kekerasan seksual.
Apabila penegak hukum dan sebagian masyarakat kita masih bias gender, bagaimana RUU PKS ini menimbang unsur keadilan antara korban dan pelaku?
Ada pembagiannya, namanya delik aduan dan delik biasa. Delik aduan itu misalnya pelecehan seksual, yang tidak ada serangan tetapi ungkapan, tidak harus dilanjutkan. Apabila pelaku meminta maaf dan korban mencabut laporannya, itu boleh, bisa. Bisa pula diselesaikan di ranah internal institusi tertentu, misalnya kalau di perusahaan ditegur secara lisan, kalau di kampus bisa ditegur, bisa pula diselesaikan melalui mekanisme komite etik. Hal ini biasanya menyangkut persoalan etika, seperti pelecehan seksual (siulan, gurauan, dan sebagainya yang berkonotasi seksual).
Kalau delik biasa, itu mengacu pada kejahatan yang serius dan dampaknya pasti pada korban. Hukumannya ada pidana pokok ataupun tambahan. Kalau pidana pokok, hukumannya bisa rehabilitasi atau penjara. Kalau tambahan, macam-macam, bisa pencabutan hak, permohonan maaf, dan lainnya. Jadi hukuman tidak selalu harus penjara, tetapi juga rehabilitasi. Beragam sifatnya. Misalnya perkosaan, itu tidak bisa delik aduan. Apalagi yang sifatnya memang sudah berpengaruh pada hidup orang. Pelecehan seksual di ranah siber, yang sudah disoroti oleh publik (seperti revenge porn), juga demikian, karena itu sudah berdampak pada hidup orang.
Judul pada RUU ini pernah sempat dibahas untuk diganti menjadi penghapusan “kejahatan seksual”, apakah kejahatan seksual dan kekerasan seksual bisa dianggap sama?
Kalau kejahatan seksual itu, ambigu. Semua itu kejahatan, tetapi kejahatan yang seperti apa? Kalau hanya kejahatan seksual, itu agak repot. Istilah kekerasan seksual itu merujuk pada bahasa baku dan sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan kita, sayangnya tidak ada definisi secara jelas. Misalnya, seperti yang ada di UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Perlindungan Anak. Makanya, kami menggunakan istilah yang memang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga kami perluas, sehingga aturan ini tidak hanya berlaku pada kelompok tertentu, tetapi pada siapapun yang bisa menjadi korban. Kalau UU Perlindungan Anak kan tidak mencakup orang dewasa. Jadi, istilah yang lebih cocok adalah kekerasan seksual. Sebab, ini mengatur kejahatan-kejahatan yang terkait dengan kekerasan seksual, bukan kejahatan seksual. Beda maknanya.
Saya sendiri berpendapat, kalau memang mau diganti, judul yang pas untuk RUU ini adalah RUU Pemberantasan Tindak Pidana Seksual. Kalau pemberantasan itu ada aspek hukum pidananya, aspek pencegahan dan penanganan lengkap di sana.
Ketika RUU PKS ini disahkan, apakah peraturan ini bisa mendorong munculnya peraturan internal seperti di sekolah, perguruan tinggi, fasilitas umum, atau dunia kerja?
Harusnya begitu. Ini bisa menjadi rujukan bagi instansi dalam membuat peraturan yang berkesusaian. Makanya, ada kewajiban yang bentuknya pencegahan, salah satunya adalah mendorong kebijakan dan sosialisasi penghapusan kekerasan seksual di berbagai bidang. Bidang-bidang yang kami masukkan adalah pendidikan, sektor tenaga kerja, dan tata ruang (seperti lampu jalan dan pengaman di tempat sepi). Ini menjadi proses yang komprehensif dalam bentuk penghapusan kekerasan seksual, mulai dari pencegahan dan penanganan.
Bila bicara mengenai isu ini di lingkungan kerja, pelecehan dan kekerasan seksual ini masuk ke unsur kelayakan kerja (decent work) serta kesehatan dan keselamatan kerja. Berarti, perusahaan atau penyedia kerja juga harus memiliki peraturan soal kekerasan seksual ini sama seperti institusi lainnya?
Harus, karena sudah banyak korban. Apalagi kalau pekerjanya ada perempuan dan rata-rata posisinya di bagian bawah, sementara manajer dan atasannya laki-laki. Sekarang WHO sudah meletakkan kekerasan seksual sebagai isu kesehatan, termasuk kesehatan mental. Jadi, sudah ada standarnya. Saya kira teman-teman di serikat buruh juga perlu mulai menyuarakan konvensi ILO tentang kekerasan seksual. Itu kan baru dibentuk dan Indonesia belum meratifikasinya. Itu bisa sebagai pintu masuk.
Bagaimana tanggapan Anda soal dicabutnya RUU PKS dari Prolegnas tahun ini? Apa yang dapat dilakukan masyarakat sipil?
Tentu saya sangat kecewa. Saya merasa pembentuk kebijakan ini tidak memberikan perhatian terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi dan dialami oleh perempuan di Indonesia. Padahal setiap hari ada kasusnya. Ini berarti pemerintah tidak begitu serius.
Soal masyarakat sipil, kita perlu terus menyuarakan pandangan secara serius dan berkelanjutan. Bisa juga langsung kepada fraksi-fraksi atau ketua-ketua partai. Partai harusnya mendukung. Ini harus menjadi isu semua pihak. Kalau misalnya Komisi VIII mengambil sikap seperti itu, berarti anggota partai mereka yang ada di sana tidak layak. Ini harus didelegitimasi. Konkretnya bagaimana? Mendesak ketua partai bersuara untuk segera mengesahkan dan menyuruh anggotanya serius membahas ini. Selain itu, tentu saja kita juga perlu mendesak pemerintah.[]