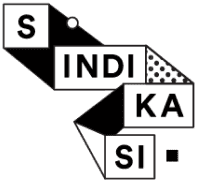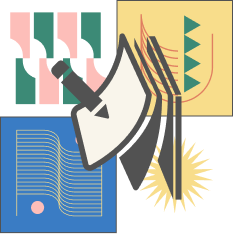Pemberedelan Pers 4.0

Beberapa hari ini ada fenomena yang menggelisahkan. Beberapa website media dikabarkan diretas. Misalnya saja yang menimpa Tempo.co yang situsnya sempat tidak bisa diakses. Sementara itu peretasan yang sampai juga menimpa Tirto di mana berita-berita yang kritis terhadap pemerintah khususnya terkait penanganan pandemi dihapus. Meskipun pada akhirnya berita yang dihapus bisa dikembalikan lagi, ini tetap saja menggelisahkan.
Saya menyebutnya sebagai pemberedalan pers 4.0. Yang menggelisahkan, kita sulit untuk menunjuk siapa yang melakukan peretasan. Namun karena itu, efeknya justru membesar karena peretas cukup yakin bisa melakukan apa saja kepada siapa saja dan percaya diri tidak akan mendapatkan hukuman apa-apa.
Kalau ditarik lebih jauh ke dalam sejarah pers di Indonesia, pemberedelan atau upaya intimidasi semacam ini bukan hal yang baru. Di era demokrasi liberal, misalnya, pers menjadi medan perdebatan sekaligus peperangan antar kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.
Soekarno menunjukkan rasa marahnya terhadap situasi yang tidak stabil yang salah satunya diakibatkan pers. Karena itu, dengan dalih revolusi ekonomi belum selesai, ia menyatakan bahwa kebebasan pers dan “kritik destruktif terhadap kepemimpinannya” tidak dapat diterima. Pers yang kontrarevolusioner harus “di-retool” untuk membangkitkan kembali semangat revolusionernya.
Edward Cecil Smith dalam buku Sejarah Pemberedalan Pers di Indonesia (1983), merekam “rasa marah” Soekarno tersebut dalam bentuk aksi-aksi kekerasan terhadap pers dan jurnalis sepanjang tahun 1949-1965. Sepanjang periode kekuasaan Soekarno tersebut, terdapat sekurangnya 561 tindakan pemerintah yang anti terhadap pers. Tindakan pemerintah ini mewujud dalam bentuk pemberedelan, penahanan wartawan, nasionalisasi pers asing, sampai penyitaan percetakan pers.
Di awal dekade 1950-an, pemberedalan yang dilakukan belum terlalu masif. Aksi-aksi kekerasan pemerintah terhadap pers masif minim karena pemerintah dan pers masih mencari modus vivendi di antara keduanya. Belum lagi, dalam sisten parlementer Soekarno belum memiliki keuntungan dan dukungan politis yang melimpah jika ia ingin melakukan pemberedalan terhadap pers yang secara keras menyerangnya dan terus melakukan provokasi politik.
Puncak aksi tindakan keras terhadap pers di era Soekarno adalah tahun 1957. Sebagaimana dicatat Smith, di tahun tersebut tindakan kekerasan terhadap pers mencapai angka 125 kali. Harian Indonesia Raya yang tidak berafiliasi dengan partai politik dan anti-komunis, menjadi surat kabar yang paling banyak mendapatkan tindakan, 13 kali. Sementara pemimpin redaksinya, Mochtar Lubis, dipenjara.
Menariknya, di tahun ketika aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah begitu tinggi, jumlah surat kabar juga mencapai posisi tertinggi, 116 surat kabar dengan oplah keseluruhan yang mencapai satu juta eksemplar. Jumlah ini di tahun-tahun selanjutnya menurun seiring kekerasan dan rangkaian pemberedelan yang dilakukan pemerintahan Soekarno. Maraknya tindakan pemberedelan selain memperlihatkan watak otoriter pemerintah juga menunjukkan betapa surat kabar begitu tergantung dengan partai politik afiliasinya, baik itu berupa finansial maupun sikap politik.
Di bawah kekuasaan rezim otoriter, negara begitu terobsesi untuk mengatur masyarakatnya. Eksistensi negara mesti melampaui individu dan masyarakat. Karena itu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh rakyatnya. Salah satunya adalah mengatur secara ketat informasi dan kebebasan pers. Sejarah mencatat bahwa Orde Baru yang diskursus pembangunannya ikut dibantu dan dilegitimasi pers (lebih lanjut cermati buku Francois Railon Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia), pada akhirnya melakukan represi dan kontrol total terhadap kehidupan pers.
Sebagaimana disebut Daniel Dhakidae, kontrol total ini berada di bawah Departemen Penerangan yang berbeda dengan departemen lainnya, merupakan titik pusat dari perwujudan gagasan ideologi sekaligus aksi represif aparat pemerintah karena memiliki peran ganda sebagai alat informasi sekaligus alat ekonomi.
Kendali absolut yang dimiliki oleh Deppen membuat pemerintah bisa mengarahkan informasi dan menjadikan Orde Baru sebagai kisah tentang pemberedalan dan represi terhadap pers. Nyaris sepanjang usia kekuasaan rezim, pers dipandang sebagai kekuatan yang mesti dilumpuhkan selumpuh-lumpuhnya. Awal kekuasaan rezim ini ditandai dengan penutupan 46 dari 163 surat kabar setelah chaos politik 1965. Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan kantor berita Antara dibersihkan dari segala unsur kiri.
Gelombang beredel selanjutnya terjadi di tahun 1974 ketika ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi mencapai puncaknya. Usai kerusuhan besar-besaran yang dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari, setidaknya 12 media diberedel dan dilarang terbit. Ironisnya, beberapa media yang diberedel tersebut seperti Harian Kami dan Mahasiswa Indonesia adalah pendukung utama Orde Baru.
Gelombang beredel ini mempertegas rusaknya hubungan antara pemerintah dengan pers yang sebelumnya samar-samar terlihat. Momen ini juga menandai kejatuhan jurnalisme politik dan sekaligus kemunculan industri pers di Indonesia. Ancaman pemberedelan dan kekerasan negara terbukti secara efektif membentuk struktur pasar media yang nanti akan berkembang semakin masif dan bertahan lama. Gerak politik yang demikian sempit – bisa dirangkum dalam istilah pers bebas dan bertanggungjawab – menjadikan pers hanya memiliki celah untuk melakukan ekspansi ekonomi dan diversifikasi produk.
Struktur pasar media yang pelan-pelan terbentuk tersebut tidak cuma melahirkan konglomerat-konglomerat media yang dilindungi oleh rezim, tetapi lebih dari itu, ia juga membawa pergeseran dalam perkembangan diskursus mengenai jurnalisme. Karena sikap kritis yang mestinya melekat sejak awal dalam karakter kebebasan pers dibonsai, apa yang muncul kemudian adalah pertumbuhan industri media minus kekuatan politisnya. Media dan wartawan berjarak dari berita-berita yang mereka produksi sendiri, bahkan ketika ingin melakukan kritik terhadap kekuasaan.
Gerak pers dari masa ke masa – tak terkecuali kekerasan dan pemberedelan – menunjukkan bahwa upaya mengkaji peran dan fungsi pers hampir sinonim dengan pembacaan terhadap sistem politik yang melingkupinya. Keduanya melekat sehingga kita tidak mungkin mengabaikan salah satunya. Sistem politik mempengaruhi keberadaan dan eksistensi pers, menentukan apa dan sejauh apa ruang geraknya. Sebaliknya, pers memiliki pengaruh signifikan dalam sebuah sistem politik dengan melanggengkan atau mendelegitimasi rezim politik yang sedang berkuasa.
Karena itu pemberedalan 4.0 ini adalah lampu kuning bagi mereka yang peduli dengan kebebasan berekspresi di Indonesia. Jika pemberedelan semacam ini terus dibiarkan, maka demokrasi kita memang sedang berjalan mundur. []
Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi SINDIKASI