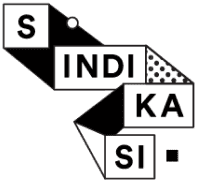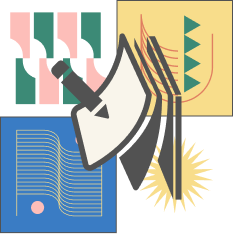Mogok Wartawan

Wartawan di Indonesia, kebanyakan dan hampir selalu menerima apa pun keputusan para bos mereka, kendati itu menyangkut nasib dan kesejahteraan mereka. Itu berbeda dengan yang dilakukan para wartawan di Inggris dan di Italia.
KETIKA pemogokan umum itu melanda London yang murung, tak seorang pun karyawan surat kabar The Times yang ikut di dalamnya. Tak pula para wartawannya. Pemimpin surat kabar itu, dengan bangga mengatakan, semua karyawan The Times setia kepada pekerjaannya, kepada profesinya dan karena itu, mereka semua tidak ikut-ikutan dengan aksi pemogokan umum.
Hari itu di pengujung 1926, di kota-kota di Inggris, para pekerja yang marah tengah menuntut pemerintah agar tidak menutup pertambangan batubara. Aksi mereka berakhir ketika pemerintah kemudian setuju untuk meningkatkan upah mereka dan menempatkan perwakilan yang memiliki kedudukan sama kuat di manajemen pabrik.
Hingga 53 tahun kemudian, ketika hampir semua orang melupakan absennya para wartawan The Times dalam aksi mogok di tahun 1926, kejadian sebaliknya dan lebih telak justru menimpa surat kabar ternama itu: The Times berhenti terbit, setelah seluruh karyawan termasuk para wartawannya melakukan aksi mogok. Berbeda dengan pemogokan umum 1926 yang hanya berlangsung beberapa hari, pemogokan para karyawan dan wartawan The Times malah berlangsung selama hampir setahun.
Tahun itu, 1978, manajemen The Times memutuskan untuk menggunakan komputer, dan rencana itu yang ditolak karyawan. Karyawan-karyawan di bagian produksi terutama, yang pekerjaan mereka antara lain menyusun huruf-huruf sebelum koran itu naik cetak, menganggap komputer akan menggantikan profesi mereka. Tapi beberapa pengamat menyalahkan The Times karena surat kabar itu gagal meyakinkan karyawan soal modernisasi dan sebaliknya memupuk keangkuhan profesi para karyawannya.
Banyak yang dirugikan dengan pemogokan itu, tentu saja. Namun para pembaca The Times bisa diyakinkan bahkan wartawan pun berhak menyuarakan kepentingannya setelah selalu menyuarakan kepentingan dari orang-orang tak berdaya. Tidakkah para pembaca itu juga tak bisa melakukan hal yang sama, melaporkan, menulis dan memberitakan seperti yang dilakukan para wartawan itu ketika mereka melihat ketidakadilan di sekitar mereka?
Pemogokan sebelas bulan yang dilakukan wartawan The Times, karena itu dimaklumi oleh mereka. Para wartawan dari media lain termasuk dari pesaing The Times, juga tidak mencoba menarik keuntungan dengan misalnya melamar dan menawarkan diri menggantikan posisi para wartawan yang mogok, agar koran itu bisa terbit kembali. Sebagian malah memberikan dukungan moral, yang lain mencarikan jalan keluar dan sebagainya, hingga The Times terbit kembali dan tuntutan para wartawannya dipenuhi.
Bertahun-tahun kemudian, setelah manajemen The Times menyadari kesalahannya dan lalu memperbaikinya, surat kabar itu menjadi salah satu koran terbaik di Inggris, bahkan hingga kini. Pemogokan di tahun 1978 itu efektif mengubah pola pikir manajemen The Times untuk memperlakukan wartawan dan karyawannya sebagai aset dan bukan sebagai sekrup kecil dari sebuah industri, yang hanya harus tunduk kepada keinginan para pemodal dan bos mereka.
Lalu bagaimana dengan wartawan di Indonesia? Hampir tidak pernah ada kejadian seperti yang menimpa The Times, yang tidak terbit hampir setahun karena para wartawannya mogok meliput, menulis dan memberitakan. Wartawan di Indonesia adalah wartawan-wartawan yang dikenal sebagai anak manis, yang kebanyakan dan hampir selalu menerima apa pun keputusan para bos mereka, kendati itu menyangkut nasib dan kesejahteraan mereka.
Sebagian karena berlindung di balik alasan profesional. Demi kesetiaan kepada profesi, untuk kepentingan pembaca dan sebagainya. Sebagian lagi beralasan mogok atau boikot hanya perbuatan para buruh pabrik yang kumuh, dan bukan pekerjaan wartawan yang intelek meski diam-diam di antara mereka, berebut makan setiap kali ada undangan liputan. Ada yang menilai, mogok sebagai perbuatan kaum kiri yang genit dan wartawan bukan bagian dari kaum itu.
Wartawan lainnya mengaku tidak bisa atau menolak melakukan aksi mogok atau boikot karena kolega mereka yang bekerja di media yang sama, tidak melakukannya. Tidak ada solidaritas, katanya, seolah hanya itu syarat sebuah pemboikotan. Singkat kata, mogok dianggap tidak efektif memperjuangkan hak mereka karena media mereka tetap akan terbit, terus tayang dan sebagainya, karena masih banyak rekan mereka yang bersedia menggantikan pekerjaan mereka, meski dengan menggerutu.
Kalau sebagian kenyataannya adalah seperti itu, lantas siapa yang akan membela para wartawan (Indonesia) ketika mereka diperlakukan tidak adil, dan pada akhirnya diberhentikan dari media tempatnya bekerja? Sumber berita, para politisi, aktivis pejuang demokrasi atau LSM-LSM itu? Tidak. Kecuali hanya menyatakan keprihatinan dan simpati, pengalaman menunjukkan, mereka semua juga selalu membisu. Hanya itu. Tidak lebih.
Orang mungkin tidak akan percaya, kejadian-kejadian menyedihkan semacam itu, benar menimpa para wartawan di Indonesia. Namun faktanya, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI adalah satu-satunya organisasi profesi wartawan di Indonesia yang mungkin paling banyak menerima pengaduan soal perlakuan semena-mena para pemilik modal dan keangkuhan bos media kepada para wartawannya. Mereka yang tidak mengadukan, saya percaya, jumlahnya lebih banyak lagi dengan alasan bermacam-macam.
Ada yang merasa tidak berdaya melakukan apa-apa bahkan jika itu hanya untuk menuntut pesangon. Itu terutama menimpa para wartawan dari media-media kecil, baik dari segi modal maupun pengaruh dan jangkauan edar. Menuntut bagi mereka hanya buang-buang waktu dan melelahkan.
Sebagian yang lain, merasa malu meramaikan kasus mereka dengan medianya karena menganggap diri sebagai kumpulan orang-orang pintar, berpendidikan, dan profesional. Mereka berpikir, apa kata dunia, kalau akhirnya tahu, kumpulan-kumpulan orang hebat itu ternyata tak berdaya menghadapi keangkuhan pemilik dan pengelola media di tempatnya bekerja. Atau bisa karena alasan lainnya. Dan atas nama semua alasan itu, mereka karena itu lebih memilih untuk tidak bersuara, sembari diam-diam mencari peluang bekerja di media lain, meloncat ke sana kemari, setelah itu kembali dengan lantang menuliskan berita soal pemecatan yang menimpa para pekerja sebuah bank, PHK masal buruh pabrik, korupsi uang negara, atau hak-hak orang lain yang dikebiri.
Tentu, itu semua soal pilihan jika tidak mungkin disebut sebagai sebuah ironi. Wartawan yang pekerjaannya telanjur dianggap sebagai pembuka kebenaran, pembela ketidakadilan, penyuara kebebasan berpendapat, membela hak-hak kaum tertindas, ternyata hanya diam tidak melakukan apa pun jika itu menyangkut nasib mereka. Lihat atau dengarlah kemudian, para wartawan itu dengan gagah bisa melakukan aksi boikot atau mogok untuk tidak meliput sebuah sumber karena persoalan sepele. Misalnya karena teman mereka dianiaya oleh sumber dan sebagainya. Mereka pula, bisa dengan berbagai alasan menghentikan tidak mengirimkan berita ke meja redaksi dengan alasan solidaritas karena nasib buruk yang menimpa rekan mereka di lapangan dan sebagainya.
Sekali lagi, semua itu memang soal pilihan. Namun kejadian yang pernah dilakukan para wartawan The Times dan yang terbaru yang dilakukan para wartawan di Italia, mungkin bisa dijadikan bahan renungan para wartawan di sini. []
Ditulis oleh Rusdi Mathari, dimuat di buku Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan (2018)