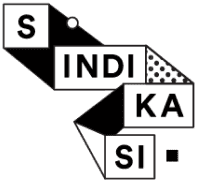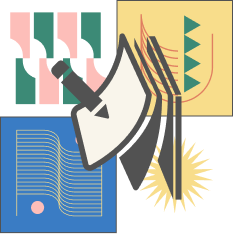Menjadi Jurnalis

Djaman sekarang, banjak sekali journalist jang gagah brani, tetapi moedah didjebak, sedang journalist jang tjerdik kebranian koerang (Marco Kartodikromo, Djawi Hiswara 13 Desember 1918)
Bandung, Januari 1907. Sekembalinya dari pengembaraan di Maluku, Tirto Adhi Soerjo menjadi jurnalis yang berbeda. Tidak seperti ketika memimpin surat kabar Soenda Berita dengan santun dan sabar, ia berubah menjadi begitu garang. Seperti dikatakan Pramoedya Ananta Toer dalam Sang Pemula (1985), dalam setiap kesempatan, Tirto kerap menggunakan tulisan-tulisannya untuk memukul kekuasaan. Pram menduga, perubahan yang drastis itu terjadi karena selama di Maluku Tirto menyaksikan kebiadaban yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda.
Pengalaman tersebut yang menabalkan dirinya untuk menerbitkan Medan Prijaji dengan delapan pedomanbahwa surat kabar (pers) harus : memberi informasi, menjadi penyuluh keadilan, memberikan bantuan hukum, menjadi tempat pengaduan orang tersia-sia, membantu orang mencari pekerjaan, menggerakkan bangsanya untuk berorganisasi atau mengorganisasi diri, membangun dan memajukan bangsanya, serta memperkuat bangsanya dengan usaha dan perdagangan. Medan Prijaji menunjukkan secara gamblang ke mana keberpihakan pers serta jurnalis harus diarahkan.
Ia menelanjangi kolonialisme. Ia menjadi suara bagi kaum yang tidak bisa bersuara. Ia menumbuhkan harapan. Ikhtiar yang menggerakkan rantai pergerakan. Tirto – meminjam istilah Takashi Shiraishi – adalah archetype bagi pemimpin pergerakan dekade berikutnya. Tentu bukan kebetulan melihat fakta bahwa kebanyakan tokoh-tokoh ini juga merupakan jurnalis yang menggunakan pers sebagai medium pergerakan. Delapan pedoman tersebut tidak hanya menandai pembentukan imajinasi sebagai sebuah bangsa tetapi jugamenancapkan tonggak awal bagi jurnalisme politik di tanah air.
Jurnalisme politik seperti itu mengurat akar sampai pasca kemerdekaan. Di era demokrasi liberal tahun 1950-an, pers masih – dengan nafas yang sama dengan era sebelumnya – menjadi pers propaganda. Kita bisa menyebut beberapa contoh : Abadi (berafiliasi dengan Masyumi), Pedoman (PSI), Harian Rakyat (PKI), Suluh Indonesia (PNI), dan Indonesia Raya (Independen, anti komunis). Pasar surat kabar saat itu dikuasai media yang berafiliasi dengan partai politik. Dominasi ini bisa dibaca dari disertasi Daniel Dhakidae The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry (1991).
Pers partai menguasai pasar dengan total 77, 77 persen (komunis 28, 57 persen, sosialisasi 18, 14 persen, Islam 11, 56 persen, nasionalis 19, 5 persen) sementara pers yang independen hanya menguasai 22, 22 persen. Harian Rakjat menjadi surat kabar terbesar dengan oplah 55.000 eksemplar per hari. Pada masa ini, pers baku hantam satu sama lain termasuk menyerang pemerintah dan menjadi corong propaganda partai politik. Saling sikut antar ideologi setidaknya bisa dilihat dari kata-kata Nyoto dalam pidato ulang tahun ke VI Harian Rakjat yang mengatakan bahwa pers kanan bukannya menghidangkan setengah kebenaran kepada pembaca-pembacanya, melainkan seperlima, dan tidak jarang sepersepuluh dari kebenaran.
Jurnalisme politik di era ini menempatkan dirinya sebagai senjata yang ofensif dan destruktif. Jurnalis berdiri di antara dua kaki, sebagai jurnalis itu sendiri, dan sebagai aktivis partai politik. Sementara kabinet jatuh bangun sebagai konsekuensi sistem parlementer, pemberontakan di berbagai daerah, dan kondisi sosial masyarakat pasca revolusi masih labil, kritikan dan serangan keras dari pers semakin memperburuk keadaan. Tak ada pilihan lain bagi pemerintah selain akhirnya melakukan pembredelan.
Edward C Smith dalam buku Pembreidalan Pers di Indonesia (1986) mencatat dengan detail bagaimana kondisi pers di era ini serta represi yang kemudian dilakukan Soekarno. Atas nama revolusi, jurnalis harus tunduk atau dikerangkeng. Langgam jurnalisme politik semacam ini sempat bertahan pasca peristiwa 1965 yang menghabisi koran-koran kiri. Namun, praktis ia terhenti setelah peristiwa malapetaka 15 Januari 1974 yang berujung pada pembredelan besar-besaran.
Jatuhnya Soeharto kerap dikatakan sebagai kebangkitan jurnalisme politik di Indonesia. Kondisi ketiadaan sensor membuat jurnalis bisa membuat berita sevulgar apapun tanpa ketakutan dibredel. Kebebasan bergerak ini memang dimiliki oleh pers namun yang perlu diperhatikan, industrialisasi pers yang dipupuk dan dibesarkan selama Orde Baru – untuk penjelasan ini kita patut berterima kasih kepada David T. Hill dengan bukunya Pers di Era Orde Baru (1994) – berperan membuat pasar menjadi stagnan.
Bisnis media bergerak dalam persaingan pasar yang semu. Konsentrasi kepemilikan media berada pada kelompok kepentingan lama di era Orde Baru. Jurnalisme politik hadir dengan wajah yang sama sekali lain bila dibandingkan dengan yang pernah ada dulu. Era ini mencatat bahwa jurnalisme digunakan untuk melayani kepentingan politik para pemilik modalnya. Wajah bopeng media ini misalnya bisa dilihat setiap menjelang pemilihan umum yang penuh iklan dan kampanye politik pemiliknya.
Padahal, Robert McChesney dalam buku Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times (1999) sudah mengingatkan, informasi politik yang terus menerus diberitakan secara homogen justru akan membuat depolitasi politik pada warga. Politik malih rupa menjadi modus hiburan yang memberikan profit bagi industri media. Terbukanya kanal-kanal media sosial membuat penetrasi informasi tersebut semakin kencang. Berita-berita “serius” dikemas dengan bungkus yang populer atau bahkan dimanipulasi agar menarik minat publik.
Saya membayangkan cukup berat menjadi jurnalis dalam era tsunami informasi seperti saat ini. Tantangannya tidak lagi sekadar menentang kekuasaan dengan gaya yang meledak-ledak. Tidak juga membentuk imajinasi kebangsaan melalui bahasa. Melampaui itu, tantangan utama adalah bagaimana menjadikan satu berita yang penting menjadi relevan untuk dikabarkan. Kalau peristiwa seperti pejabat membersihkan toilet saja diberitakan, barangkali kredo lawas jurnalisme “anjing menggigit manusia bukan berita, manusia menggigit anjing baru berita” memang sudah tidak berlaku. []
Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi SINDIKASI