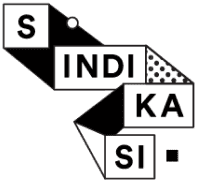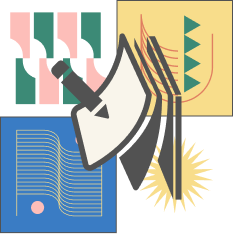Mengenal Gig Economy

Tren hubungan kontrak antara pekerja dan perusahaan, serta semakin maraknya pekerja lepas, telah melahirkan banyak diskusi akademik yang salah satunya membahas gig economy. Istilah gig erat dengan ungkapan para musisi ketika mereka menerima suatu pekerjaan dalam satu set, atau untuk merujuk pertunjukan yang terjadi dalam semalam. Saat ini, sebutan itu menggambarkan berbagai pekerjaan yang lebih luas. Pekerja gig saat ini dipekerjakan di kedai kopi, ruang kuliah universitas, peternakan, pabrik, dan sebagai petugas kebersihan. Mereka disewa perusahaan untuk gig (kerja) di bawah pengaturan “fleksibel” sebagai “kontraktor independen” atau “konsultan” untuk menyelesaikan tugas tertentu, dalam jangka waktu tertentu, dan tanpa lebih banyak hubungan dengan penyedia kerja.
Sejarah gig economy tertanam dalam sejarah internet dan proses bisnis internasional. Gagasan bahwa pekerja individu dapat berpartisipasi secara berarti dalam ekonomi global melalui internet dan alih daya dimulai sekitar tahun 1980-an dengan konsep offshore outsourcing (Graham et.al., 2017). Sebuah konsep alih daya lintas negara ini menjadi hal yang menarik di beberapa kawasan seperti Asia Tenggara. Bermula dari India karena beberapa hal (masa lalu kolonial, liberalisasi pasar oleh pemerintah, tenaga kerja terampil, dan kluster inovasi perusahaan), praktik gig economy semakin masif setelah adanya perluasan kabel serat optik di seluruh Atlantik. Dalam konteks ini, platform kerja gig online, sebagai platform yang bermodelkan hubungan antara kontraktor dan klien independen, menghadirkan jalan baru bagi pemilik usaha kecil hingga menengah yang bersedia memperkerjakan pekerja di lokasi alih daya yang sebelumnya belum dimanfaatkan (Graham, et.al., 2017: 3-4). Singkatnya, platform ini bertindak layaknya layanan perjodohan.
Para pekerja gig digambarkan secara berbeda dalam relasi sosial pekerjaan atau bentuk kontraknya, bukan teknologi atau jenis pekerjaan yang mereka kuasai. Bagi jenis-jenis pekerjaan yang berjangka panjang, posisi dan penghasilan biasanya tergantung pada masa kerjanya. Posisi dan imbalan di masa depan (seperti promosi kenaikan pangkat atau pensiun) ditentukan oleh kinerja saat ini. Sebaliknya, posisi dan penghasilan dalam pekerjaan gig economy umumnya tidak lekang oleh waktu: mereka dipekerjakan tanpa memperhatikan akumulasi masa lalu mereka. Janji pekerjaan di masa depan, uang pensiun, dan jaminan sosial biasanya ditangguhkan. Mempekerjakan mereka membuat perusahaan dapat menyesuaikan pekerjaan dan upah lebih fleksibel; untuk mengurangi risiko fluktuasi ekonomi (Friedman, 2014). Sebagai akibatnya, upah yang diterima para pekerja gig bervariasi. Bagi para pekerja harian seperti penata taman atau tukang ojek online, upah yang diterima relatif rendah. Sedangkan, upah tinggi diberikan kepada mereka yang bekerja sebagai instalasi IT, akuntan, editor, pengacara, dan konsultan.
Secara konsep, platform kerja gig yang kebanyakan memanfaatkan media dalam jaringan (daring) atau online ini dapat menghadirkan beberapa keuntungan bagi sebagian pekerja. Para pendukungnya beranggapan bahwa model pekerjaan ini dapat memungkinkan mereka untuk mencari kondisi terbaik untuk bekerja (soal ruang dan waktu), digaji ketika mereka tengah meningkatkan kemampuan atau memperkaya pengalaman mereka, dan sebagainya (Greenwald, 2012; Greenwald and Katz, 2012). Gig economy juga memungkinkan pekerja mengeksplorasi kemampuan dan hobi mereka. Tidak ada lagi yang harus merasa bosan bekerja di perusahaan yang sama selama bertahun-tahun. Melalui konsep ini pula, seseorang dapat menjadi pengacara paruh waktu sekaligus fotografer amatir dalam waktu bersamaan (Horowitz, 2011).
Pada sisi lainnya, keuntungan tersebut juga diikuti konsekuensi lain yang harus ditanggung oleh pekerja. Graham et. al. (2017) menunjukkan bahwa pekerjaan ini turut memiliki konsekuensi yang mungkin memberatkan para pekerja, seperti kelebihan pasokan tenaga kerja, ketidakamanan kerja, diskriminasi, terisolasi secara sosial, hingga terlalu banyak bekerja (overwork). Bagi para pekerja yang “dijodohkan” melalui alih daya, mereka rentan terhadap isu-isu seperti kejelasan tanggung jawab penyedia kerja, kebijakan perpajakan, dan pihak perantara.
Pekerjaan gig (gig work) merupakan salah satu fenomena yang berkelindan dengan (atau bahkan hadir untuk turut mewujudkan) pasar tenaga kerja fleksibel. Dalam pasar tenaga kerja fleksibel, dinamika ketenagakerjaan diserahkan langsung kepada hubungan antara pemodal dengan para pekerja atau pencari kerja. Rezim ini memiliki karakter berupa gagasannya terhadap pekerja bebas yang kemudian dapat mempengaruhi pergerakan buruh (Tjandraningsih dan Nugroho, 2009). Fungsi pekerja bebas sendiri adalah mengalokasikan jasanya demi merespons pergantian upah relatif, sementara perusahaan dapat dengan bebas menyesuaikannya untuk menanggulangi pergantian kesempatan keuntungan relatif. Jalan ini ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi dengan cara membersihkan apa yang dianggap memberatkan atau “kaku”.
Praktik kerja yang memanfaatkan platform digital ini sama sekali bukan hal baru yang didorong atau diperparah semata-mata oleh teknologi. Teknologi dalam rangkaian ini hanya memfasilitasi penerapan strategi ekstraksi tenaga kerja manajemen lama yang sama tuanya dengan kapitalisme, bahkan mungkin lebih tua. Pekerjaan sesuai permintaan (on-demand work) dan kompensasi kerja borongan telah umum diterapkan di banyak industri, mengingat kegunaan mereka (dalam situasi tertentu) untuk memastikan bahwa pemberi kerja hanya membayar pekerjaan yang benar-benar mereka butuhkan dan terima (Grantham, 2002). Sementara itu, pekerja lepas, musiman, dan kontrak adalah bentuk utama pekerjaan berbayar ketika kapitalisme pertama kali muncul dan terkonsolidasi (Deakin, 2000; Wood, 2002). Dalam banyak temuan di lapangan (seperti beberapa temuan yang telah dikemukakan sebelumnya), gig economy telah memilih bentuk produktif mereka sebagai kontraktor karena alasan efisiensi dan hukum. Pihak swasta ingin menghindari hak atau tunjangan yang biasanya harus dibayarkan oleh mereka, menghindari dampak standar pengaturan yang berlaku untuk pekerjaan (upah minimum dan batasan jam kerja), dan yang paling penting mentransfer risiko fluktuasi kondisi permintaan dari pasar.
Kekuatan sekaligus prasyarat utama untuk mewujudkan gig economy adalah keberadaan kumpulan surplus tenaga kerja yang terus menerus dan substansial (Stanford, 2017). Apa itu surplus tenaga kerja? Surplus tenaga kerja atau relative surplus population merupakan sejumlah kaum pekerja yang tersedia dalam jumlah berlebih dan ada demi keperluan akumulasi modal pada tingkat perkembangan perkonomian kapitalis tertentu (Neilson dan Stubss, 2011). Kemunculan kelompok ini merupakan dampak sekaligus kondisi yang diperlukan dalam akumulasi kapital. Dalam perspektif ini, kapital tidak mungkin menguntungkan dirinya sendiri pada pertumbuhan penduduk alami. Para pemilik kapital perlu secara aktif menciptakan suatu cadangan populasi pekerja yang sewaktu-waktu dapat dipanggil.
Salah satu contoh peran surplus tenaga kerja ini dapat digambarkan melalui fungsi upah yang dimainkannya. Penentuan upah secara jelas mencerminkan pengaruh lembaga pengatur yang terlibat di dalamnya (seperti undang-undang upah minimum, aturan mengenai serikat pekerja dan perundingan bersama, serta praktik dan lembaga pengatur upah lainnya). Saat pengangguran semakin parah, biaya kehilangan pekerjaan akan lebih tinggi – karena pekerja butuh waktu untuk mencari pekerjaan baru – dan pekerja yang telah mendapatkan pekerjaan pada umumnya akan merasakan keterpaksaan yang lebih besar untuk memenuhi tuntutan di tempat kerjanya, meskipun kondisinya tidak layak (Dore, 2003; Campbell dan Price, 2016).
Stanford (2017) turut menunjukkan bahwa kebangkitan pekerjaan berbasis platform digital mencerminkan suatu strategi organisasi kerja. Teknologi, lebih-lebih digital, hanya memfasilitasi suatu penerapan strategi ekstraksi tenaga kerja yang gunanya untuk melakukan kontrol terhadap pekerja atas pekerjaan mereka—sehingga pengusaha dapat mencapai upaya dan produktivitas yang optimal dari karyawan upahan mereka (Burawoy, 1979). Strategi ini meliputi kekuatan makroekonomi, politik ekonomi, dan peraturan yang lebih luas yang juga memasukkan penghitungan ekstrasi tenaga kerja dalam berbagai cara (Stanford, 2017).
Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengenalkan gig economy sebagai sesuatu yang yang tidak terelakkan. Sebaliknya, penulis berusaha menunjukkan bahwa gig economy justru memantik kita untuk mempertimbangkan kembali kebijakan sosial yang tepat bagi kelas pekerja, atau lebih tepatnya menarik kita pada pertarungan ini. Para pendukung gig economy benar bahwa dobrakan terhadap organisasi yang kaku dan pasar tenaga kerja internal dapat membebaskan pekerja individu maupun pebisnis. Masalahnya adalah menemukan cara untuk memperluas otonomi individu sambil memberikan keamanan dan komunitas melalui bentuk-bentuk baru dukungan sosial, baik melalui program negara ataupun bantuan timbal balik yang diperbarui (Friedman, 2014). Memperbaiki dan memperluas jaring pengaman perlindungan sosial dan jaminan pendapatan dapat meningkatkan daya tawar semua pekerja untuk menuntut perlakuan timbal balik yang wajar dan layak dari pemberi kerja mereka. Agenda ini tentu perlu dilakukan bersama, sebagaimana slogan yang berbunyi “Do Together What You Can’t Do Alone”. []