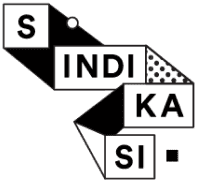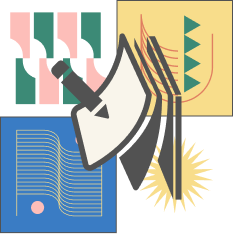Kerentanan Pekerja Fleksibel, Apa Penyebabnya?

Periode 1980-an, beberapa akademisi ilmu sosial arus utama sempat mengasumsikan bahwa mobilisasi buruh atau kelompok berbasis kelas telah usang. Salah satu argumennya menyebutkan bahwa globalisasi telah menciptakan kompetisi antar pekerja di seluruh dunia dan berdampak pada kekuatan serta kesejahteraan buruh (Zolberg 1995). Bagi akademisi lainnya, asumsi ini mengundang bahaya karena dapat berakibat pada “lenyapnya analisis mengenai kapitalisme dalam literatur gerakan sosial” (Silver 2013; Silver & Karatasli 2015).
Konflik yang terjadi antara buruh dan pemilik kapital dapat ditelusuri di “tempat tinggal” tersembunyi dari sebuah mekanisme produksi. Sebagai sebuah tatanan sosial, sejarah kapitalisme identik dengan komodifikasi tenaga kerja. Tingkat dan intensitas eksploitasi ini merupakan hubungan endemik antara buruh dan pemilik modal. Polanyi (1944) mengidentifikasi bahwa fokus dasar perjuangan ini berada pada pasar tenaga kerja. Selama komoditas buruh adalah “manusia itu sendiri di setiap masyarakat berada”, maka untuk “menyertakan mereka dalam mekanisme pasar berarti menundukkan substansi mereka terhadap hukum pasar itu sendiri”. Dari sinilah kita mengenal pasar tenaga kerja.
Karakter dari kapitalisme adalah perubahan yang terjadi tanpa henti sehingga ia bukanlah sistem yang statis. Dalam sejarah, pemilik kapital menanggapi pergerakan tenaga kerja dengan serangkaian strategi yang ditempuh untuk mengurangi biaya mereka dan meningkatkan kontrol pada produksi. Strategi ini dapat berdampak pada pembentuk maupun tidak terbentuknya kelas pekerja hingga memperkuat maupun memperlemah daya tawar pekerja yang terjadi secara tidak merata (Silver 2014).
Bila perspektif tersebut digunakan untuk melihat konteks Indonesia, barangkali kita bisa memeriksa, bagaimana dengan pasar tenaga kerja di Indonesia? Buruh di masa pasca-Soeharto (tidak jauh dari periode 1980-an) pada dasarnya diatur melalui rezim neoliberal karena fenomena ekonomi politik yang berkelindan di antaranya (Rudiono 1992). Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 turut membuka jalan bagi lebih banyak langkah liberalisasi ekonomi, salah satunya membentuk pasar tenaga kerja fleksibel. Hal ini berdampak pada dinamika yang terjadi pada pasar tenaga kerja kita diserahkan pada hubungan antara pemodal dengan para pekerja atau pencari kerja. Rezim ini memiliki karakter berupa gagasannya mengenai pekerja bebas yang kemudian dapat mempengaruhi pergerakan buruh (Tjandraningsih & Nugroho 2009). Fungsi pekerja bebas sendiri adalah mengalokasikan jasanya demi merespons pergantian upah relatif. Sementara, perusahaan dapat menyesuaikan dan menanggulangi pergantian kesempatan keuntungan relatif. Jalan ini ditempuh untuk meningkatkan kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi dengan cara membersihkan apa saja yang dianggap memberatkan atau “kaku”.
Upaya pembersihan terhadap hal-hal kaku itu salah satunya dilakukan melalui berbagai kebijakan dan aturan di tingkat negara. Kebijakan ini pun seringkali mengundang kontra dari para pekerja karena dirasa memberatkan. Salah satu momen yang bisa menjadi contohnya adalah aksi buruh pada May Day tahun 2006. Ratusan ribu pekerja turun ke jalan di banyak kota di seluruh negeri ini untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Bagi buruh, perubahan aturan itu dapat membuat pasar tenaga kerja Indonesia lebih fleksibel dengan merelaksasi beberapa perlindungan tenaga kerja. Tanpa revisi yang diusulkan tahun 2006, UU Ketenagakerjaan telah memperkenalkan kontrak kerja tidak tetap dan praktik alih daya untuk pasar tenaga kerja Indonesia. Fleksibilitas tenaga kerja dengan demikian bukan melonggarkan peraturan/regulasi pasar tenaga kerja, melainkan menyediakan alternatif bagi lembaga regulasi yang lebih mengutamakan pengusaha daripada pekerja.
Oleh karena itu, buruh merasa perlu menolak revisi yang diajukan pemerintah. Pemerintah dan komunitas bisnis berpendapat bahwa revisi ini diperlukan demi menggenjot ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi Asia tahun 1997. Akan tetapi, nyatanya, kebijakan ini justru mengenalkan lebih banyak kekuatan pasar dan penghapusan langkah-langkah perlindungan di pasar tenaga kerja. Salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan efisiensi di Indonesia adalah dengan mengenalkan Private Employment Agency (PEA) atau agensi tenaga kerja swasta. Pengenalannya pada UU No. 13 Tahun 2003 membuat PEA berfungsi memisahkan tenaga kerja dari pemiliknya (penyedia kerja) dan menjual mereka ke perusahaan klien sebagai faktor produksi (Juliawan 2010). Informalisasi pekerja dengan demikian tercipta dari fleksibilitas pasar tenaga kerja yang semakin intensif dan tidak adanya lagi perlindungan dari negara.
Sejak tahun 1970-an, ada sebuah peningkatan proporsi pekerja di sektor informal yang konsisten di ranah global. Penelitian Chang (2009) merupakan salah satu yang menunjukkannya. Di banyak negara Asia, informalisasi sektor formal telah diperluas secara masif. Hal ini membuat hubungan kerja menjadi tidak stabil dan sering tidak langsung. Ada tiga bentuk informalisasi yang diidentifitikasi yaitu gerakan ke dalam kegiatan produksi kecil dengan rendahnya produktivitas dan pendapatan, perusahaan memberi informasi ketenagakerjaan dengan menggunakan subkontrak pekerja dan pekerja alih daya, serta penggunaan bentuk pekerjaan ilegal. Ketiganya dilembagakan oleh kebijakan negara sekaligus relatif tidak ada keterlibatan negara yang dilakukan secara eksplisit (Arnold dan Bongiovi 2013).
Ekspansi kontemporer diperkuat oleh produksi dan kompetisi global. Bagi Indonesia, kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel merupakan salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia dalam tahapan pemberian bantuan program pemulihan ekonomi negara. Restrukturisasi pasar tenaga kerja dirinci dalam poin 42 dari Letter of Intent (LoI) ke-21 antara Indonesia dan IMF. Konteksnya untuk meningkatkan iklim investasi dalam rangka perbaikan ekonomi. Hal inilah yang kemudian menjadi rujukan untuk perumusan kebijakan termasuk UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan turunan peraturan lainnya termasuk di daerah. Fleksibilitas ini merupakan rezim yang kuat. Ia diciptakan melalui kolaborasi oleh berbagai aktor, kebijakan, dan institusi untuk “melenturkan” semua aspek produksi dan hubungan kerja demi memaksimalkan peluang untungnya pemodal (Tjandraningsih & Nugroho 2009).
Rangkaian kondisi ini sedikit banyak lantas berpengaruh terhadap berbagai kondisi kerja yang rentan. Mulai dari pemecatan sepihak di tengah kontrak, kelelahan bekerja, upah dibayar di bawah ketentuan tetapi jam dan beban kerja tetap tinggi, hingga mempengaruhi daya tawar para pekerja termasuk serikat buruh. Kombinasi fleksibilisasi dan informalisasi dengan demikian dapat melemahkan para pekerja secara ekonomi maupun politik. Secara ekonomi, mereka cenderung memiliki taraf hidup yang rendah akibat pekerjaan yang tidak layak (indecent work), serta dipaksa berkompetisi satu sama lain akibat surplus pekerja di pasar tenaga kerja yang di saat bersamaan juga dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol upah. Secara politik, selain kompetisi antar pekerja satu sama lain, mereka juga tidak mampu (relatif susah) “melawan” karena terpecah secara spasial sehingga tidak mampu membentuk organisasi kolektif dan melawan/menuntut kenaikan taraf kerja di tempat mereka bekerja. []