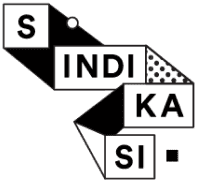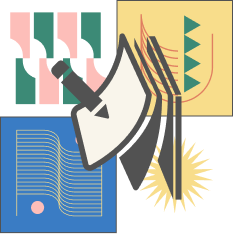Ekonomi Digital: Antara Ambisi Negara dan Kerentanan Pekerja (Bagian 2)

Bagian pertama tulisan ini sudah membahas mengenai ambisi negara serta kerentanan pekerja di era ekonomi digital. Catatan berikutnya terkait lanskap baru ini adalah adanya eksploitasi yang dilakukan oleh aktor-aktor lama dalam kemasan baru. Disrupsi teknologi yang mempengaruhi pola dan model ekonomi yang saat ini berimbas pada banyak ketidaksiapan, terutama dari pihak yang semestinya berfungsi sebagai regulator.
Dalam audiensi yang dilakukan oleh SINDIKASI dengan Kementerian Ketenagakerjaan pada 5 Januari 2018, misalnya, Menteri Ketenagakerjaan saat itu Hanif Dhakiri mengakui ekonomi kreatif dan digital ini merupakan “hutan belantara yang belum diketahui seluk beluknya”. Pembuatan regulasi sendiri dikhawatirkan dianggap sebagai penghambat bagi investasi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan industri baru. Padahal, banyak relasi ketenagakerjaan yang belum bisa terakomodir dalam relasi yang berlangsung sekarang ini, terutama: pekerja freelance yang semakin meningkat jumlahnya, pekerja muda dan program magang dimarakkan, penyelewengan ikatan kerja dalam narasi sharing economy seperti “mitra” serta “konsultan” yang dialami oleh para pengemudi transportasi daring dan kantor berita, maupun relasi kerja outsource bagi pekerja di mata rantai produksi utama seperti di production house, agensi periklanan, dan lain sebagainya.
Sampai artikel ini ditulis, dari pihak regulator, hanya Kementerian Perindustrian yang memiliki dokumen terkait dengan ekonomi digital, yaitu Making Indonesia 4.0 yang diterbitkan lewat situs resmi kementerian. Selain Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Industri, idealnya Kementerian Keuangan seharusnya memiliki peranan penting dalam menentukan pola praktik ekonomi digital, yang juga berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan dari segi regulator. Ketiadaan regulasi terkoordinasi dari pelayan publik tidak mampu bergerak mengejar kecepatan disrupsi saat ini.
Meski demikian, pada dasarnya tidak ada yang baru dalam Revolusi Industri 4.0. Ia hanya perpanjangan sirkuit rantai produksi komoditas menggunakan perangkat digital. Salah satu praktik paling terlihat adalah konvergensi media di Indonesia. Menurut penelitian Ross Tapsell, Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens, and The Digital Revolution (2017), praktik ini tidak hanya melahirkan kondisi kualitas produk kognitif yang dihasilkan (dalam kasus ini adalah berita), tapi juga pada buruknya kondisi pekerja.

Hal tersebut senada dengan posisi Kementerian Perindustrian melalui Making Indonesia 4.0, yakni sebuah cetak biru terkait Revolusi Industri 4.0 di Indonesia yang menyasar pada 5 sektor utama untuk penerapan awal teknologi ini, yakni (i) makanan-minuman, (ii) tekstil-pakaian, (iii) otomotif, (iv) kimia, dan (v) elektronik; bahwa adaptasi terhadap ekonomi digital adalah upaya revitalisasi industri manufaktur—atau bila kita sebut dalam perspektif kritis terhadap kapitalisme: ekonomi digital/Revolusi Industri 4.0 adalah upaya akselerasi konsumsi-produksi.
Untuk merevitalisasi industri manufaktur, Indonesia berkomitmen untuk mempercepat implementasi 4IR [4th Industrial Revolution]. Inisiatif Making Indonesia 4.0 ini memberikan potensi besar untuk melipatgandakan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing global dan mengangkat pangsa pasar ekspor global. Ekspor yang lebih tinggi akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, sehingga konsumsi domestik menjadi lebih kuat dan Indonesia dapat menjadi salah satu dari 10 besar ekonomi dunia.
Pihak pengusaha dianggap sebagai pemegang peranan penting dalam ekonomi tersebut. Sejauh ini, yang menjadi referensi bagi pemerintah dalam membangun strategi menghadapi ekonomi digital adalah para pemodal internasional, seperti perwakilan/pemodal/venture capitalists Silicon Valley (AS) dan Jack Ma (Ali Baba-China), serta pengusaha unicorn lokal—yang acapkali belum bisa mengakomodir pekerja.
Contoh lain nampak dari sejumlah perambahan ranah digital, baik pendanaan start-up maupun pendanaan aktivasi dilakukan oleh pemodal “lama” seperti Djarum Group yang mendanai sejumlah media digital. Sejumlah konglomerat Indonesia juga mengembangkan sayapnya untuk berinvestasi dalam ekonomi digital, antara lain: Sinar Mas Group, The Hartono Family, The Riady Family, dan The Salim Family lewat aktivitas sebagai venture capital, pemilikan saham atau pembentukan perusahaan baru berbasis digital.
Kondisi ini sekiranya memperkuat premis Daniel Marcus Greene dan Daniel Joseph dalam paper mereka berjudul “The Digital Spatial Fix” (tripleC, 2015) yang mengontekstualisasi ekonomi digital dengan premis David Harvey mengenai spatial fix: bahwa praktik ekonomi digital pada dasarnya adalah konsekuensi logis bagi para kapitalis untuk mengekspansi ruang (space) untuk menjaga keberlangsungan akumulasi kapital di tengah krisis yang dihadapi kapitalisme itu sendiri. Dengan kata lain: revolusi industri 4.0 sampai berapa titik kosong pun, ketika ia bergerak dengan model ekonomi kapitalistik yang sama, maka hanya akan menawarkan model eksploitasi lama bagi kelas pekerja—hanya bajunya saja yang berbeda.
Dengan konteks tersebut menjadi masuk akal bagi kita untuk menarik kata kunci kunci utama dalam era ekonomi disruptif ini: outsourcing atau alihdaya. Bagi pegiat serikat buruh dari rantai manufaktur, outsourcing atau alihdaya adalah persoalan yang tak baru dan terus berlangsung hingga saat ini. Namun, dalam konteks ekonomi digital ini, alihdaya yang dimaksud untuk bisa kita kritisi bukan hanya dalam relasi alihdaya tenaga kerja, melainkan juga seluruh instrumen produksi dan reproduksi pekerja. Hal ini bisa dilihat dengan narasi “pekerja independen” atau “pekerja kreatif mandiri” dimana pekerja menyediakan sendiri alat produksi mereka untuk kepentingan akumulasi kapital pengusaha, seperti pada freelancer yang menyediakan sendiri komputer, koneksi internet, ruang kerja atau pada mitra ojek daring yang menyediakan sendiri motor, bensin, dan maskernya termasuk jaminan sosial dan kesehatan mereka sendiri.
Pada titik ini, sebagai upaya untuk menghadapi fleksibilitas, atomisasi, dan kerentanan yang terus meningkat, dibutuhkan bentuk-bentuk kolektif pekerja yang mampu mengintervensi ketimpangan regulasi. Organisasi ini juga harus mampu menjadi ruang pengaman bersama bagi para pekerja rentan digital dan pekerja kognitif (digital precariat and cognitariat).
Serikat pekerja menjadi bentuk yang paling akomodatif dalam merespon kondisi ketenagakerjaan ini. Berbeda dengan inisiatif berbentuk asosiasi profesi yang sulit mengakomodasi kepentingan pekerja. Bentuk lain seperti himpunan pekerja tingkat perusahaan atau komunitas, pun kapasitas geraknya kurang koheren dan influential, bentuk serikat pekerja dengan kapasitas gerak formal dan politisnya memiliki potensi mumpuni untuk hadir dalam relasi tripartite dan menjadi representasi dari pekerja industri media dan kreatif, di mana mayoritas pekerjanya telah dibuat merasa mengambang dari politik.
Serikat pekerja ekonomi digital juga dapat menjadi wadah untuk mengartikulasikan kembali kesadaran pekerja baik secara individual maupun kolektif. Termasuk dalam mendekatkan pengetahuan dasar mengenai hak-hak normatif pekerja; sekaligus untuk mengembangkan pola-relasi kerja alternatif untuk menghadapi rantai eksploitasi yang terus membelit.
Bagi pekerja, serikat pekerja 4.0 harus bisa berakselerasi untuk mengejar dan menghadapi pola-pola eksploitasi sebagai konsekuensi logis kapitalisme disruptif. Salah satu langkah ideal adalah dengan memanfaatkan secara penuh perkembangan teknologi, dan menguasai balik teknologi tersebut. Penguasaan ini sebetulnya dimaksudkan untuk menyiasati atomisasi pekerja yang bersifat lintas waktu dan tempat, sekaligus menguasai balik data dan domain digital dalam mengorganisir diri. Strategi presentasi diri yang kontekstual, relevan, dan dekat dengan audiens juga menjadi langkah penting untuk diambil, sekaligus mendobrak stigma negatif dan persepsi buruk di mata publik terhadap serikat pekerja sebagai akibat laten dari penghancuran sistematis gerakan kiri di Indonesia oleh Orde Baru (misalnya melalui TAP MPRS no. 25/1996). Sikap ini membendung akses publik atas pembacaan dan pemikiran kritis melihat kerja. Pendekatan komunikasi friendly, jenaka, kreatif, dan tepat sasaran harus dapat salah satu bangunan citra utama yang harus dirakit.
Di samping itu, saat berdialog dengan para pemangku kebijakan, serikat pekerja 4.0 juga perlu secara aktif mendesak pemerintah agar kebijakan yang ada menyisakan ruang bagi pekerja atau bahkan bersifat pro-pekerja (bukan hanya mengakomodir teknokrat, regulator, dan pemodal), termasuk dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Industri, Keuangan, serta lembaga terkait industri masing-masing. Dibutuhkan juga upaya dan kampanye khusus untuk mengintervensi kesadaran publik mengenai romantisme, pengaburan dan fleksibilitas kerja yang bersifat eksploitatif. []
Ditulis oleh Ellena Ekarahendy, Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)