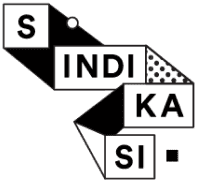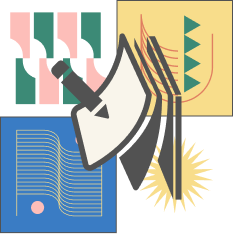Gerak Perjuangan Pekerja dalam Kontrol Pasar Tenaga Kerja

Sebagai salah satu penganut rezim kontrol pasar tenaga kerja (market labor control regimes), Indonesia sebenarnya telah menghadapkan para pekerjanya dalam daya tawar yang rendah selama krisis ekonomi (Anner 2015). Hal ini dapat terjadi karena tingginya pengangguran memaksa para pekerja untuk menerima kondisi kerja yang buruk dan membuat mereka berhati-hati dalam mengatur serikat pekerja karena mudah digantikan. Peningkatan fleksibilisasi pasar tenaga kerja telah menyebabkan terjadinya market despotism yang merupakan kembalinya bentuk kontrol “lama” melalui kekuatan pasar yang koersif, di mana pasar digunakan sebagai cambuk untuk mendisiplinkan pekerja (Webster et al. 2008). Setiap dinamika pasar tenaga kerja dapat meningkatkan rasa kerentanan pekerja – baik peningkatan pekerjaan paruh waktu, kontrak jangka pendek, atau tenaga kerja alih daya – sehingga akan meningkatkan kontrol terhadap tenaga kerja pula. Akibatnya, pekerja cenderung bertahan dengan kondisi buruk dan upah rendah daripada berisiko menganggur dan jatuh dalam kemiskinan, karena takut jika berbicara banyak mengenai kondisi kerjanya mereka dapat kehilangan pekerjaan (Anner 2015: 3-5).
Bagaimana konteks tersebut berdampak pada ekosistem kerja digital? Wood et al. (2018) mengidentifikasi bentuk organisasi mandiri yang ada di antara para pekerja lepas digital. Penelitian atas negara-negara berpendapatan menengah (Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara) itu menyebutkan, organisasi kolektif di antara pekerja lepas online cenderung mengambil bentuk kelompok media sosial dalam penataan komunikasinya dan tidak memiliki serikat pekerja. Komunitas internet, dengan demikian, memainkan peran vital dalam pengalaman kerja para pekerja lepas digital. Melalui komunitas berbasis internet ini, mereka saling mendukung dan berbagi informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keamanan dan perlindungan mereka. Selain itu, dalam penelitian itu juga disebutkan bahwa hanya sedikit dari para pekerja lepas ini yang merasa kehadiran serikat pekerja akan menguntungkan mereka. Sikap apatis ini berasal dari kombinasi persepsi serikat yang sudah ada sebelumnya dan manfaat dari serikat pekerja tidak akan melebihi risiko kehilangan pekerjaan dan pajak yang lebih besar (Wood et al. 2018: 107-108).
Komunitas internet ini terfragmentasi oleh kebangsaan, pekerjaan, dan platform yang berbeda-beda, yang mana, sebagaimana dikemukakan Silver (2003), cenderung membatasi skalabilitas potensial aksi kolektif. Walaupun begitu, komunitas pekerja tetap dapat bergabung secara efektif (misalnya dimediasi oleh kelompok dan forum berbasis nasional) untuk mempengaruhi platform dan klien, karena pekerja, klien, dan platform dari pekerjaan rata-rata berada di tingkat regional atau lokal.
Selain itu, sangat mungkin bagi serikat pekerja untuk melawan atau mengatasi hambatan geografis ini bila mereka mendekati para pekerja yang belum bergabung dengan serikat pekerja lepas yang telah berhasil di sektor lainnya (Heery et al. 2004; King 2014). Sebab, absennya serikat pekerja cenderung membatasi kemampuan para pekerja untuk memenangkan hasil hubungan industri (Saundry et al. 2012) dan juga dapat membatasi kesediaan pekerja untuk mengajukan tuntutan hukum atas pengakuan hak-hak buruh atas dasar status mereka (Cruz et al. 2016). Pilihan lainnya adalah menghubungi komunitas pekerja lepas online yang telah ada untuk bergabung dalam serikat pekerja sebagaimana disarankan oleh Saundry et al. (2012).
Untuk konteks Indonesia sendiri, sejarah mengenai hubungan antara pergerakan pekerja dan sayap politik dapat memberikan kita gambaran akan tantangan yang mungkin dihadapi. Menurut Ford (2005), warisan struktur gerakan buruh pada periode pasca-kemerdekaan (1945-1965) dan cara rezim Soeharto mengutuk keterlibatan gerakan buruh terorganisasi dalam pemilihan umum dan proses politik formal telah membuat jurang pemisah antara gerakan buruh dan ranah politik. Di bawah rezim Orde Baru Soeharto, pekerja telah dilarang keras mengembangkan ikatan dengan partai politik atau terlibat dalam cara lainnya sekalipun dalam politik pemilu. Tujuannya, rezim ingin memanfaatkan pekerja untuk mencapai pembangunan nasional, yang mana hal ini juga dilatarbelakangi oleh ketakutan terhadap kembalinya “kekacauan politik” yang sempat terjadi pada tahun 1965. Meskipun sebagian besar masalah yang menyebabkan gagalnya formalisasi hak-hak pekerja ini datang dari serikat sendiri, menurut Ford (2004), banyak dari generasi aktivis ketenagakerjaan saat ini masih dipengaruhi oleh definisi sosial-ekonomi serikat pekerja sebagaimana yang ditunjukkan dalam sikap partai-partai “buruh” di Pemilu tahun 1999 dan 2004 (Ford 2004: 201-202).
Meski demikian, seperti yang disinggung di atas, di tengah kegagalan mengembangkan partai-partai buruh dan tripartisme fungsional, kelompok buruh telah tumbuh untuk menerima aksi protes jalanan sebagai strategi mereka. Juliawan (2011) menunjukkan, berbagai generasi pemimpin serikat pekerja dan aktivis buruh, terutama di tingkat akar rumput, mulai bermunculan dan melakukan program pelatihan kepemimpinan yang efektif. Walaupun begitu, hal ini tidak bisa serta merta dijadikan sebagai bahan optimis akan arah politik perburuhan Indoensia di masa depan. Tindakan kolektif kemungkinan akan tetap menjadi mekanisme utama untuk melibatkan negara selama bertahun-tahun yang akan datang, sebab ia berbuah hasil (Juliawan 2011: 363-366). Gerakan buruh akan terus menjadi jaring aktivis dan serikat pekerja yang longgar dan terdesentralisasi tanpa kepemimpinan pusat yang kuat. Dengan demikian, dalam jangka waktu yang relatif lama, strategi ini akan berjalan begini adanya selama taktik lain yang lebih konvensional untuk berurusan dengan negara dan pengusaha mengalami hambatan.
Di samping aksi protes di jalanan, banyak anak muda semakin sering mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah atau elite secara daring. Platform media digital terkadang menjadi jalan pertama, jika tidak bisa disebut pelengkap, untuk menjangkau dan memanggil solidaritas secara lebih luas, juga menyebarkan materi kampanye dan tuntutan dari aksi protes mereka sebelum turun ke jalan. Dari sini kita memahami bahwa baik oligarki maupun warga sama-sama diberdayakan oleh digitalisasi. Tapsell (2018: 219-225) menelaah tiga cara pemberdayaan warga Indonesia yang difasilitasi oleh digitalisasi: proses demokrasi, pembentukan wacana publik, dan mendorong reformasi kebijakan. Sementara, ketegangan antara agensi ini dengan negara juga tidak bisa dielakkan. Fakta bahwa negara dan oligarki terus berstrategi untuk membungkam agensi-agensi ini melalui dalih pencemaran nama baik dan UU ITE masih terus terjadi hingga hari ini. Meski demikian, tekanan dari bawah ini tetap diperlukan untuk menciptakan perubahan sedikit demi sedikit. Konflik dan eksperimen berisiko semacam itu sedikit demi sedikit akan sangat penting menentukan hasilnya.
Pemanfaatan ruang digital untuk mendukung, memperkuat, maupun menjaga keberlanjutan gerakan patut dilakukan untuk menuntut perubahan lebih baik akan ekosistem kerja para pekerja digital. Terlebih ketika kita sepakat bahwa pengorganisasian terhadap serikat pekerja di seluruh dunia semakin menemukan relevansinya, sebagaimana digagas oleh Breman dan Linden (2014). Walaupun jalannya barangkali masih panjang, bila semakin banyak warga sadar akan maksud-maksud perubahan mereka, maka akan semakin signifikan transisi yang dipicu sesuai dengan keinginannya, baik melalui pemanfaatan teknologi, aksi protes di jalanan, maupun strategi lainnya.