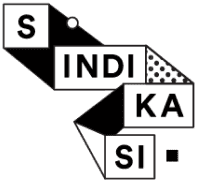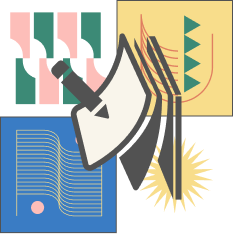Bertahun-tahun Menunda RUU PKS

Hasil rapat koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi I-XI 30 Juni 2020 menyepakati DPR menunda sejumlah pembahasan legislasi, salah satunya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). DPR beralasan pandemi Covid-19 membuat mereka memiliki keterbatasan membahas legislasi yang sebelumnya masuk Prolegnas 2020.
Sementara Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan angka kasus yang makin tinggi. Sepanjang 2019 ada 4.898 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Laporan tentang kekerasan seksual paling banyak ditemukan di ranah publik, dengan kasus pencabulan (531), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara di ranah pribadi, kekerasan seksual jadi yang kedua terbanyak setelah kekerasan fisik.
Secara umum, kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2019 naik 6% dibanding tahun sebelumnya, dari 406.178 pada 2018 menjadi 431.471 sepanjang 2019. Banyaknya kasus menunjukkan urgensi agar RUU PKS segera disahkan. Komnas Perempuan dalam rilis persnya menyebut penundaan berulang ini menimbulkan dugaan bahwa sebagian besar anggota DPR belum memahami situasi genting kekerasan seksual di Indonesia. Padahal RUU ini sudah dinantikan selama bertahun-tahun untuk melindungi korban.
Ide tentang pentingnya payung hukum untuk memberantas kekerasan seksual bermula dari temuan tingginya angka kasus sepanjang 2001-2011. Sepanjang satu dekade tersebut, 25% kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Setiap hari setidaknya 35 perempuan jadi korban kekerasan seksual. Artinya, setiap jam ada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual hingga Komnas Perempuan menyebut Indonesia darurat kekerasan seksual.
Pada 2011 Komnas Perempuan meneliti jenis-jenis kekerasan seksual dan mencatat ada 15 bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi di Indonesia. Di tahun yang sama, mereka juga mendata kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun. Laporan tersebut dirilis pada 2012 sekaligus memulai usulan pembentukan payung hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual.
“Ada draft awal di tahun 2012, itu sudah sampai ke DPR dan diterima, tetapi belum menjadi pembahasan,” kata Sri Wiyanti Eddyono, dosen Fakultas Hukum UGM.
Pada 2015 Sri Wiyanti bersama Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, dan DPD menyusun naskah akademis dan menyelesaikan draft RUU. Isinya seputar tindak pidana kekerasan seksual, seperti kontrol, intimidasi, eksploitasi, penyiksaan seksual, dan pemaksaan aborsi. RUU juga menjabarkan mengenai hak korban atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Dari 15 bentuk kekerasan seksual, ada 9 yang diatur, yakni eksploitasi dan penyiksaan seksual juga pemaksaan aborsi, kontrasepsi, perkawinan dan lain-lain.
Pada sidang 6 Juni 2016 RUU PKS masuk dalam daftar prolegnas prioritas Prorgram Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2017 dan menjadi inisiatif DPR. Setahun kemudian, Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah koordinasi berbagai kementerian terkait RUU PKS.
“DPR sendiri menunjuk Komisi VIII sebagai panitia kerja (panja) baru pada awal 2018. Dan sejauh ini panja baru sampai Rapat Dengar Pendapat Umum, semacam konsultasi dengan para pakar, termasuk ormas-ormas besar di Indonesia,” kata Masruchah seperti dikabarkan Historia.
Setelah masuk prolegnas, pemerintah membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sayangnya, draft dari DPR dipotong hingga 2/3 bagian. Menurut Sri Wiyanti hal itu menjadi salah satu penyebab pembahasan RUU ini agak ramai dan sulit. DIM yang dibuat oleh pemerintah agak jauh dari yang dibuat oleh inisiatif DPR.
Sepanjang 2019, draft RUU kembali disusun namun akhirnya mentok dan dikeluarkan dari Prolegnas 2019. Pembahasan kemudian dilimpahkan pada DPR 2020 namun menemui kebuntuan karna tidak ada kesepahaman substansi antara pemerintah dan DPR.
“Maret sudah ada surat dari Komisi VIII yang berisi permintaan dikeluarkannya draft ini dalam Prolegnas. Tetapi, semakin mengerucut akhir-akhir ini,” kata Sri Wiyanti.
Beragam Upaya dari Masa Lalu
Keengganan DPR membahas RUU PKS mengecewakan banyak pihak. Padahal, keberadaan RUU ini amat penting untuk melindungi korban kekerasan seksual. RUU ini menginginkan adanya payung hukum yang jelas pada segala tindak kekerasan seksual yang sudah tidak bisa lagi dituntaskan oleh delik pidana yang telah ada sebelumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah pelecehan seksual tidak dikenal. KUHP hanya mencakup perbuatan cabul (pasal 284 dan 293) dan perkosaan (pasal 285).
Selain itu ada pula UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. UU ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut penandatanganan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women, CEDAW) pada 1981. Penandatanganan CEDAW bermula dari usaha feminis negara dunia pertama yang berhasil memasukkan dekade perempuan (1975-1985) dalam agenda PBB. Menyusul kemudian Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women, CEDAW) keluar pada 1979.
Deklarasi ini dibahas dalam Konferensi Dekade Perempuan PBB di Kopenhagen pada 29 Juli 1980. Indonesia sepakat untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus diskriminasi terhadap perempuan dari beragam spektrum, salah satunya kekerasan seksual.
Namun, kasus yang menjadi sorotan utama gerakan perempuan saat itu adalah pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga. Pasalnya, aturan hukum yang berlaku kala itu, yakni KUHP 285 mendefinisikan perkosaan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan kepada perempuan yang bukan istrinya. Sehingga perkosaan dalam rumah tangga dianggap tidak ada.
Kalyanamitra, YLBHI, dan organisasi perempuan lainnya berusaha mengajukan usulan untuk membentuk payung hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Proses pengusulan hingga disahkannya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memakan waktu amat panjang, 12 tahun.
“Waktu itu masih relatif berat sekali untuk mengatur bentuk pelecehan ataupun kekerasan seksual yang lebih luas, jadi akhirnya kami pikir yang penting saat ini (peraturan yang mengatur kekerasan seksual, red.) dalam rumah tangga dulu,” kata Sri Wiyanti.
RUU lain yang diusulkan untuk menciptakan negara yang lebih adil pada perempuan ialah RUU Kesetaraan Gender dan RUU Pekerja Rumah Tangga. Keduanya juga masih belum disahkan. Usaha ini masih menemui jalan terjal ketika DPR memutuskan untuk menghapus (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional 2020. Perjuangan panjang untuk menghapus kekerasan seksual masih terus berlanjut. []